Tulisan ini adalah catatan reflektif perjalanan saya bersama beberapa sahabat relawan ke Lopo Bambu, Taman Baca SMP Katolik San Daniel Oepoli, Kupang pada tanggal 5-7 Juli 2021.
Tujuan perjalanan saya adalah kunjungan literasi bagi anak-anak di Taman Baca SMP Katolik San Daniel, sembari membawa beberapa paket buku yang telah saya kumpulkan sendiri maupun yang saya peroleh dari keringanan tangan teman-teman donatur.
Saya juga ingin membawa sejumlah dana sebagai bantuan bagi kelancaran aktivitas literasi di Taman Baca Lopo Bambu bagi anak-anak perbatasan itu. Dana ini pun hasil sumbangan dari para donatur yang membeli buku saya Membaca Peristiwa (Kumpulan Artikel yang diterbitkan oleh Penerbit Dusun Flobamora). Buku ini saya intensikan secara khusus penjualannya untuk aktivitas literasi anak-anak di Oepoli.
Mendengar Cerita, Menumbuhkan Cinta
Sebelumnya, saya hanya mendengar cerita tentang kondisi anak-anak di Oepoli pada umumnya, dan anak-anak di Lopo Bambu khususnya, dari media dan juga sharing orang-orang yang pernah mengunjungi ataupun tinggal di Oepoli. Saya mengikuti beberapa postingan RD. Januario Gonzaga, Kepala Sekolah SMP Katolik San Daniel di media sosial pribadinya, maupun media sosial sekolah.
Melihat semangat anak-anak perbatasan, yang dalam banyak hal, mengalami keterbatasan akses, khususnya akses pada buku-buku, menumbuhkan cinta dalam hati saya untuk membangun satu proyek sederhana: penerbitan buku untuk membantu mereka.
Saya percaya, menulis adalah juga aktivitas pengungkapan cinta. Seorang penulis juga, secara moral, terikat dengan tanggung jawab sosial. Itulah yang saya perjuangkan.
Dalam kesadaran kritis, saya tidak memposisikan diri saya sebagai seseorang yang “superior” di hadapan mereka. Dalam banyak hal, ketimpangan “sejak dalam pikiran” mengisi banyak kesadaran orang-orang kota berhadapan dengan orang-orang di luar kota.
Dalam skema asimetris ini, banyak agenda baik dari pemerintah maupun non pemerintah akhirnya menjadikan orang-orang yang berada di luar akses pusat pembangunan dan perkembangan sebagai “korban”, atau paling tidak, sebagai “yang inferior” (yang butuh belas kasih, yang tidak berdaya, dll) daripada melihat mereka sebagai partner perkembangan kemanusiaan yang setara, yang tentu dalam beberapa aspek, mengalami kemalangan.
Refleksi personal ini saya tulis dalam bagian pengantar buku saya Membaca Peristiwa demikian “Atas izin Romo Januario Gonzaga selaku Kepala Sekolah SMP Katolik San Daniel Oepoli Kupang, saya ingin mendonasikan keuntungan dari penjualan buku ini untuk pengadaan buku-buku bacaan yang layak bagi anak-anak yang sedang memperjuangkan cita-cita mereka.
Saya tidak menganggap mereka sebagai pihak kecil dan tertinggal, sebab dalam banyak hal, ketertinggalan masyarakat yang kita anggap sebagai ‘orang pinggiran’ itu akibat ketidakadilan dalam berbagai hal, khususnya dalam pelbagai bentuk kebijakan publik, juga mungkin pada preferensi-preferensi hidup kita yang tidak ramah terhadap kebutuhan sesama, atau mungkin juga karena kegilaan atas mitos kemajuan (modernitas) yang akhirnya membentuk pola pikir kita sebagai kelompok superior.
Dalam banyak hal, konstruk berpikir yang asimetris (saya kota, mereka kampung, saya maju, mereka terbelakang, dan lainnya yang serupa) inilah yang mengawetkan ketidakadilan dalam semua lini kehidupan.
Pramoedya Ananta Toer pernah mengatakan: “seorang terpelajar haruslah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Dengan demikian, membantu mereka tak lain adalah membantu diri saya sendiri, yakni menyelamatkan diri saya dari sikap ingat diri dan puas diri (Arum, 2021, hlm. 11).
Literasi Kritis dan Masalah Ketimpangan Sosial
Gerakan literasi yang selama ini menggaung secara nasional, maupun secara regional di NTT tentu saja membuka pintu harapan terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakat. Banyak taman baca didirikan di pelbagai wilayah pelosok, baik atas keprihatinan personal, kelompok, maupun juga melalui program yang diinisiasi oleh pemerintah.
Banyak Taman Baca Masyarakat di daerah-daerah mulai tumbuh dan menggerakkan semangat berliterasi. Tentu saja, masalah utama yang sedang dihadapi oleh para pegiat literasi ini adalah kemampuan membaca dalam arti yang sangat terbatas, yakni: mengenal aksara dan memperoleh pemahaman terhadap bacaan.
Pengertian literasi yang jangkauannya minimalis ini tentu sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang masih kesulitan untuk mengenal aksara, apalagi menulis.
Namun, terlepas dari penelusuran hal-hal teknis tentang bagaimana mengenal aksara, membunyikannya, dan menulis secara sederhana, apa tujuan terjauh dari gerakkan literasi ini? Untuk kepentingan tulisan ini, saya merujuk pada pengertian literasi dari National Institute for Literacy.
Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat.
Definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dengan demikian, prospek pendampingan literasi perlu memperhatikan konteks di mana aktivitas literasi itu dicanangkan.
Kemampuan teknis “baca, tulis, hitung” merupakan hal yang penting. Namun, gerakan literasi tidak hanya, atau bahkan tidak boleh berhenti pada jangkauan minimalis seperti itu. Seorang pegiat literasi perlu membangun kesadaran kritis tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah-daerah tertentu. Bagaimana kondisi sosio-kultural menjadi peluang atau tantangan bagi aktivitas literasi di tempat itu.
Bagi saya, banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang mengalami pelbagai ketimpangan sosial. Jika seorang pegiat literasi datang dengan “imajinasi kemajuan kehidupan a la kota” maka semangat yang ditumbuhkan kepada anak-anak tak lebih pada penggiringan imajinasi.
Sejatinya, kemampuan literasi dasar (baca, tulis, hitung) harus membuka akses perkembangan bagi tiap anak untuk memperoleh horizon pengetahuan yang luas, sekaligus mengambil jarak kritis dengan pelbagai ketimpangan yang dialami dalam hidupnya.
Perangkat pengetahuan harus menjadi “senjata cahaya” bagi anak-anak untuk menyusun masa depannya, menggali potensi diri dan daerahnya serta mengkritik pelbagai ketimpangan yang dialami. Misalnya, dengan kemampuan dasar membaca, anak-anak mampu mengakses banyak pengetahuan dari buku-buku untuk membuka horizon berpikirnya.
Dengan memiliki kemampuan berhitung, seorang anak di Oepoli misalnya, tidak mudah dikelabui oleh orang-orang yang hendak memeras mereka di pasar, atau bahkan dalam perkara penjualan tanah.
Dengan memiliki kemampuan menulis, seorang anak di perbatasan mampu membahasakan kehidupan dan keprihatinan mereka secara orisinal, daripada hanya direifikasi menjadi “angka statistik” orang-orang tertinggal dalam kebijakan pemerintah.
Paling kurang, ada beberapa masalah ketimpangan yang dialami oleh anak-anak di perbatasan. Masalah ini penting untuk dikaji karena punya relasi yang sangat erat dengan pendidikan sebagai jalan untuk membantu perkembangan mutu hidup anak-anak sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Pertama, keterbatasan akses bacaan. Anak-anak masih asing dengan bacaan-bacaan yang mampu memperluas horizon berpikir mereka. Bahkan, buku-buku yang terkait dengan kurikulum saja masih minim. Hal ini diperparah dengan keterbatasan akses internet sehingga menyulitkan mereka untuk mengakses informasi yang lebih luas.
Perlu diketahui, akses sinyal baru saja masuk tahun lalu ke daerah Oepoli. Dari sini, kita bisa bayangkan betapa mereka akan sangat kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat, misalnya dalam konteks pandemi ini, tentang kebijakan “Belajar Daring” atau tentang kebijakan mentereng “Literasi Teknologi”, dll. Mereka dijejali kebijakan yang sejak awal diperparah dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang mereka terima sebagai “dosa warisan” tanpa mampu membantah.
Kedua, keterbatasan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan dan represi tuntutan budaya. Banyak orang tua masih menganggap pendidikan belum memiliki manfaat yang signifikan terhadap hidup mereka, terutama matapencaharian mereka sebagai petani dan peternak.
Dalam kesadaran patriarkis yang sangat kuat, anak-anak perempuan menjadi pihak yang paling kurang beruntung. Banyak anak yang putus sekolah, atau hanya menamatkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah hanya karena dipandang sudah mampu untuk mandiri dan mengurus keluarga. Artinya, masa depan mereka seakan telah “didefinisikan” oleh warisan berpikir yang sangat sempit.
Kecenderungan untuk tidak memberi ruang bagi perempuan untuk berbicara akhirnya membuat mereka taat secara pasif dan mengubur mimpi serta cita-cita mereka. Di sesi awal pertemuan dengan anak-anak Lopo Bambu, saya bertanya tentang cita-cita dan impian hidup mereka.
Mayoritas anak yang hadir adalah perempuan. Dengan menyaksikan semangat yang luar biasa itu, saya merasa miris jika mimpi-mimpi yang mereka ungkapkan dengan lantang di ruang kelas itu akan berakhir di balik bantal sebagai bunga tidur mereka.
Baca Juga: Ketika Buku Lebih Menarik dari Bermain
Untuk itu, literasi kritis adalah jalan tempuh yang relevan untuk menyikapi pelbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak perbatasan ini. Menurut Elisabeth Bishop, literasi kritis dibangun dengan memanfaatkan eksplorasi terhadap batas-batas identitas personal, sosiopolitik, ekonomi dan intelektual. Literasi kritis, lanjut Bishop, mesti berdiri di atas landasan etis, untuk menguji sejauh mana ketimpangan struktural dapat dibaca dalam kaitannya dengan kekerasan struktusal dan sistem kekuasaan (Lawi, 2021, hlm. 68-69).
Dengan mengakses pendidikan yang layak, mereka mampu membangun hidup mereka dan membongkar pelbagai ketimpangan yang dialami oleh diri mereka, keluarga dan masyarakat yang berada di lingkungan hidup mereka. Setidaknya, mata rantai pewarisan pandangan hidup yang sempit dapat diputuskan pada generasi mereka.
Dengan cara ini pula, mereka dapat membangun daerah mereka sendiri, daripada tergiur dengan aneka tawaran imajiner tentang situasi kehidupan kota, yang dalam banyak hal, mengorbankan hidup mereka, terutama masalah human trafficking yang dialami oleh banyak anak perempuan di wilayah pedalaman NTT.
Agenda Bersama
Pelbagai masalah yang saya ungkapkan dalam tulisan ini tentu saja tidak memuat seluruh aspek probelmatika kehidupan yang dialami anak-anak di daerah perbatasan Oepoli. Dan tentu saja, masalah-masalah ini juga tidak bisa digeneralisir secara total untuk semua wilayah di NTT. Namun, catatan ini penting untuk memantik kesadaran semua pihak yang terlibat dalam upaya pendidikan dan literasi anak-anak di daerah perbatasan.
Mengingat konsep etika wajah Levinas, saya percaya wajah anak-anak di perbatasan adalah wajah yang menyuarakan sabda etis untuk membantu mereka. Wajah yang sering dianggap sepele dengan pola berpikir kita yang sudah timpang.
Dengan menjumpai secara langsung wajah anak-anak perbatasan dengan semangat yang tinggi untuk menikmati “keadilan dalam pendidikan” memberikan banyak nutrisi bagi kesadaran saya dan beberapa teman relawan bahwa semangat literasi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, di manapun mereka berada, harus dimulai dengan suatu sikap cinta yang tidak melihat kondisi mereka secara timpang, melainkan memandang mereka sebagai pribadi yang setara.
Tulisan ini juga sekaligus menjadi catatan kritis untuk upaya literasi yang melulu birokratis dan teknis tanpa upaya membangun suatu ekosistem yang melibatkan banyak pihak dan berkelanjutan. Kita tentu perlu merasa bahagia dengan turut membantu perkembangan anak-anak di wilayah pedalaman.
Namun, jangan sampai kita hadir dengan pola pikir yang timpang dengan selalu membayangkan diri sebagai kelompok superior (literat) yang memiliki segalanya untuk ditransfer kepada anak-anak di pedalaman.
Kita sering membawa imajinasi tentang perkembangan kota yang menterang, menanamkan preverensi tentang cita-cita a la kota sehingga membuat mereka menganggap bahwa kembali ke kampung mereka dan membangun kampung mereka sendiri menjadi hal yang sangat kuno.
Demikianlah akhirnya, anak-anak perempuan kampung menganggap aktivitas menenun tidak lebih bermartabat daripada menjadi seorang PNS, atau mengolah lahan pertanian dan perkebunan tidak lebih mulia daripada menjadi seorang pegawai kantor.
Dengan imajinasi ini, banyak warisan budaya mulai terancam pundah dan konflik pencaplokan dan penjualan tanah menyasar hidup mereka.
Inilah agenda kita bersama. Kita tentu mengharapkan bahwa pendidikan menjadi jalan hidup bagi semua orang untuk mengaktualisasikan diri mereka secara optimal dan bermartabat. Semoga banyak anak-anak di perbatasan, misalnya di Oepoli dan daerah-daerah lainnya tidak kehilangan kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka.

Oleh: Giovanni A. L Arum
Baca juga tulisan lain di kolom Corak atau tulisan menarik lainnya dari Giovanni A. L Arum



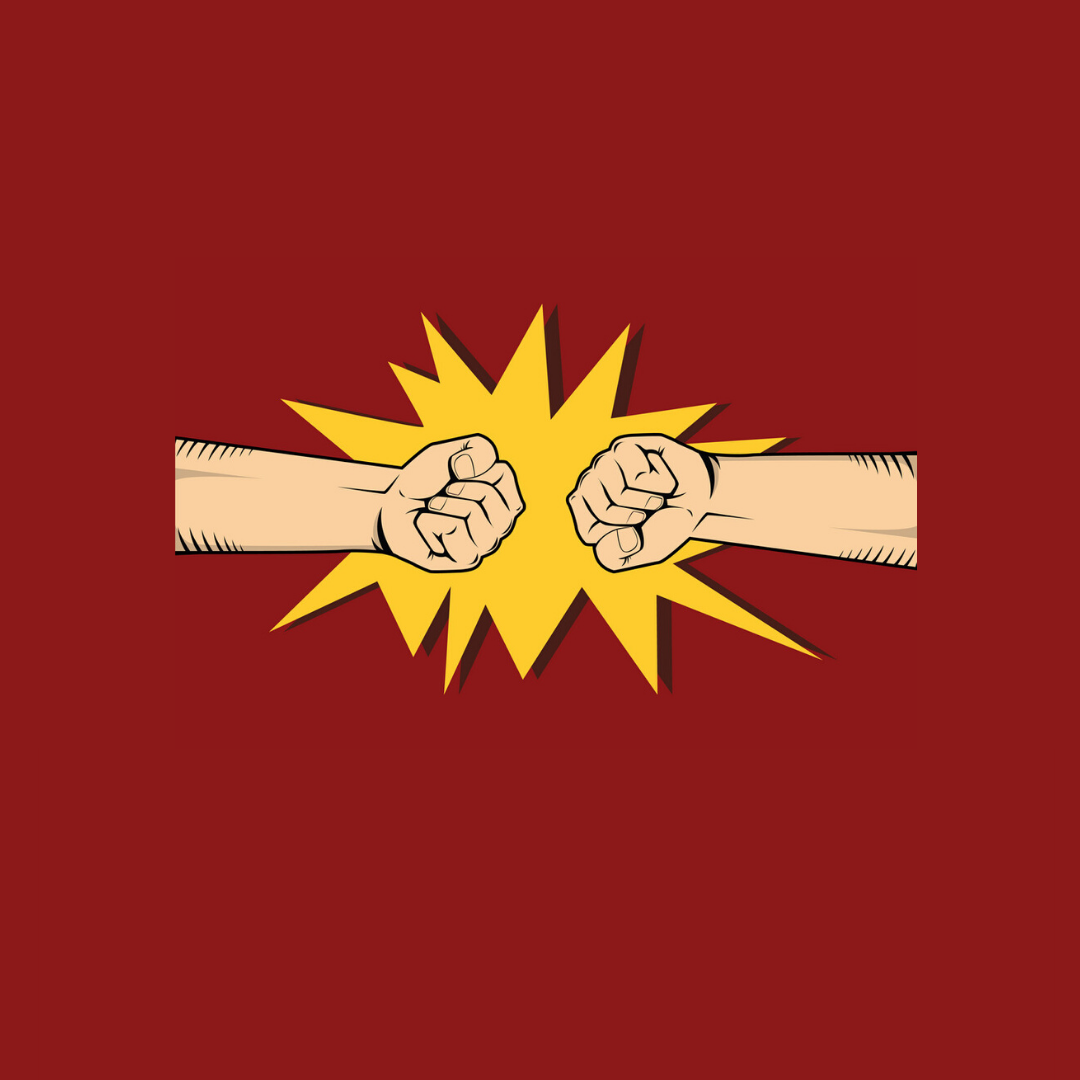

Terima kasih untuk kisah perjumpaan dan pengalaman yang mengesankan. Semoga semakin banyak orang yang sedia menghidupkan spirit literasi, khususnya bagi anak-anak dan kaum muda di daerah 3T.