Kawan-kawan yang baik, situasi kita sedang sangat sulit. Covid-19 masih terus menghantui kita, pemerintah pun tak mau kalah menyusahkan rakyatnya.
Omnibus Law dan represi yang dialami Masyarakat Adat Besipae jadi 2 dari begitu banyak contoh yang bisa kita sebutkan pada masa pandemi global ini, manakalah negara hadir bukan untuk mengatasi bellum omnium contra omnes (perang semua lawan semua), tetapi tampil gagah-perkasa sembari memfasilitasi homo homini lupus. Hari-hari ini, kita agaknya tampil sebagai serigala bagi yang lain, oleh sebab kealpaan negara.
Kendati begitu, dengan terus menagih janji dan tanggung jawab negara, saya ingin berbagi cerita.
Saya masih ingat persis, tahun 2011, facebook sama sekali belum populer, baik di Bajawa-Flores pada umumnya, khususnya di Seminari Mataloko, Flores, NTT.
Saya memang pernah mendengar orang mulai membicarakannya, tetapi sama sekali belum tahu, apa dan bagimana facebook itu.
Namun, entah karena apa, sudah saya lupa, pada liburan panjang selepas UN SMA, saya memutuskan untuk membuat sebuah akun facebook, yang kemudian bertahan sampai sekarang.
Ini kenangan yang tiba-tiba terlintas di benak saya, ketika tema tentang “antropologi internet” didiskusikan dalam kuliah Cyberteologi, saat saya masih kuliah di STFK Ledalero, Maumere, beberapa tahun silam.
Tentunya, ini tema menarik. Internet ternyata dapat dieksplorasi secara lebih mendalam, selain bahwa ia mampu memberikan banyak, bahkan hampir semua hal.
Ada sisi-sisi lain dari internet yang masih jarang disadari dan diangkat, salah satunya ialah bahwa manusia sebagai pencipta dan pengguna internet, dapat pula diselisik dalam internet itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi, tema ini menarik.
Ikut Arus (?)
Kembali ke facebook. Awalnya, saya hanya memiliki satu dunia, yakni dunia riil. Namun, setelah aktif di facebook, saya mulai menyadari bahwa ternyata, saya serentak memiliki dunia lain, dunia maya. Itulah “saya”.
Apabila merunut kembali jejak-jejak awal aktifnya saya di facebook, di situ saya menemukan bahwa sebetulnya, seperti kebanyakan facebookers lainnya, saya terjebak dalam apa yang disebut sebagai “ikut arus”.
Dalam “ikut arus”, seseorang lebih condong terpengaruh secara kuantitatif (banyaknya teman atau keluarga atau rekan kerja), daripada secara kualitatif (misalnya melalui sebuah kajian serius atau refleksi mendalam).
Baca Juga: Akun Palsu
Benar bahwa secara emosional, jejaring internet termasuk facebook merupakan sebuah ruang yang “panas”. “Panas” karena sifatnya yang terbuka, yang tanpa batas (unlimited).
Facebook termasuk salah satu social networking platform yang paling populer. Jejaring seperti facebook tidak hanya menghubungkan satu orang dengan orang lain di dunia tanpa batas, tetapi juga menciptakan komunikasi berdasarkan profil, kegemaran, dan terutama pencitraan.
Keterbukaan yang nyaris total ini memungkinkan saya terseret dalam sosialisasi yang intens, interaksi yang meluas, pun pula spontanisme yang tanpa sadar. Bermula dari “ikut arus”, identitas saya juga turut dibentuk.
Saya ke “Saya” Kembali ke Saya
Dalam perjalanan aktifnya saya di facebook, saya kerap kali mengambil jeda untuk sejenak merenung. Saya menemukan, di dunia maya terjadi apa yang boleh saya sebut sebagai ketercerabutan diri (self-deprivation). Dalam lain perkataan, saya yang berpindah menuju “saya”, membawa serta diri saya menjadi “diri saya” yang lain.
Ada jurang antara saya dan “saya”. Saya yang tidak pernah menemukan hal-hal lain di dunia nyata, akan menemukan hal-hal lain itu di dunia maya. “Saya” yang begitu mudah tertarik pada hal-hal tertentu, tidaklah sama dengan saya di dunia nyata.
“Saya” yang begitu mudah tertarik pada hal-hal tertentu, tidaklah sama dengan saya di dunia nyata.
Sederhananya, beda dunia, beda identitas: saya dan “saya” di dunia nyata dan dunia maya.
Sampai di sini, kira-kira, intisari apa yang dapat saya petik dari topik tentang “antropologi internet”?
Baca Juga: Budak Sosmed
Yang pasti, saya yang juga “saya” itu, mesti segera kembali menuju saya yang paling autentik. Saya dalam dunia nyata. Pertama-tama, saya mesti melek internet.
Artinya, tetap selaras zaman, hanya saja mesti dibarengi dengan sikap kritis dan kemampuan membatasi diri. Ini kiranya poin kunci. Sosialisasi yang intens di dunia maya, mesti tetap dibarengi dengan nilai-nilai universal yang rasional.
Interaksi yang meluas di dunia maya, mesti tetap disertai dengan kesadaran akan keunikan dan martabat setiap orang. Saya mesti juga merasa tidak bebas dalam dunia maya yang amat bebas itu.
Selanjutnya, awasan Paus Emeritus Benediktus XVI saya sangka baik untuk diperhatikan. Dunia maya tidak serta merta menggusur orisinalitas diri. Saya sebagai persona, perlu untuk tampil autentik. Selain itu, sebagai imago Dei, saya bahkan tidak dapat menyangkalnya, dalam hal yang paling kecil dan lumrah sekalipun.
Ini berarti, meskipun telah amat populer, facebook perlu digunakan dan disikapi secara lebih teliti. Bahwa facebook membawa juga banyak kontribusi positif, ini patut disyukuri. Hanya saja, tidak boleh selamanya “ikut arus”. Saya yang menjadi “saya” harus selalu kembali menuju saya.
Akhirnya, Kawan-kawan, judul artikel ini dapat digantik dengan nama masing-masing Anda, warganet terkasih. Situasi kita memang sedang benar-benar sulit. Namun saya yakin, refleksi ini bukan untuk saya semata-mata. ***
![]()
Oleh: Reinard L. Meo
Baca juga tulisan lain di kolom Corak atau tulisan menarik lainnya dari Reinard L. Meo



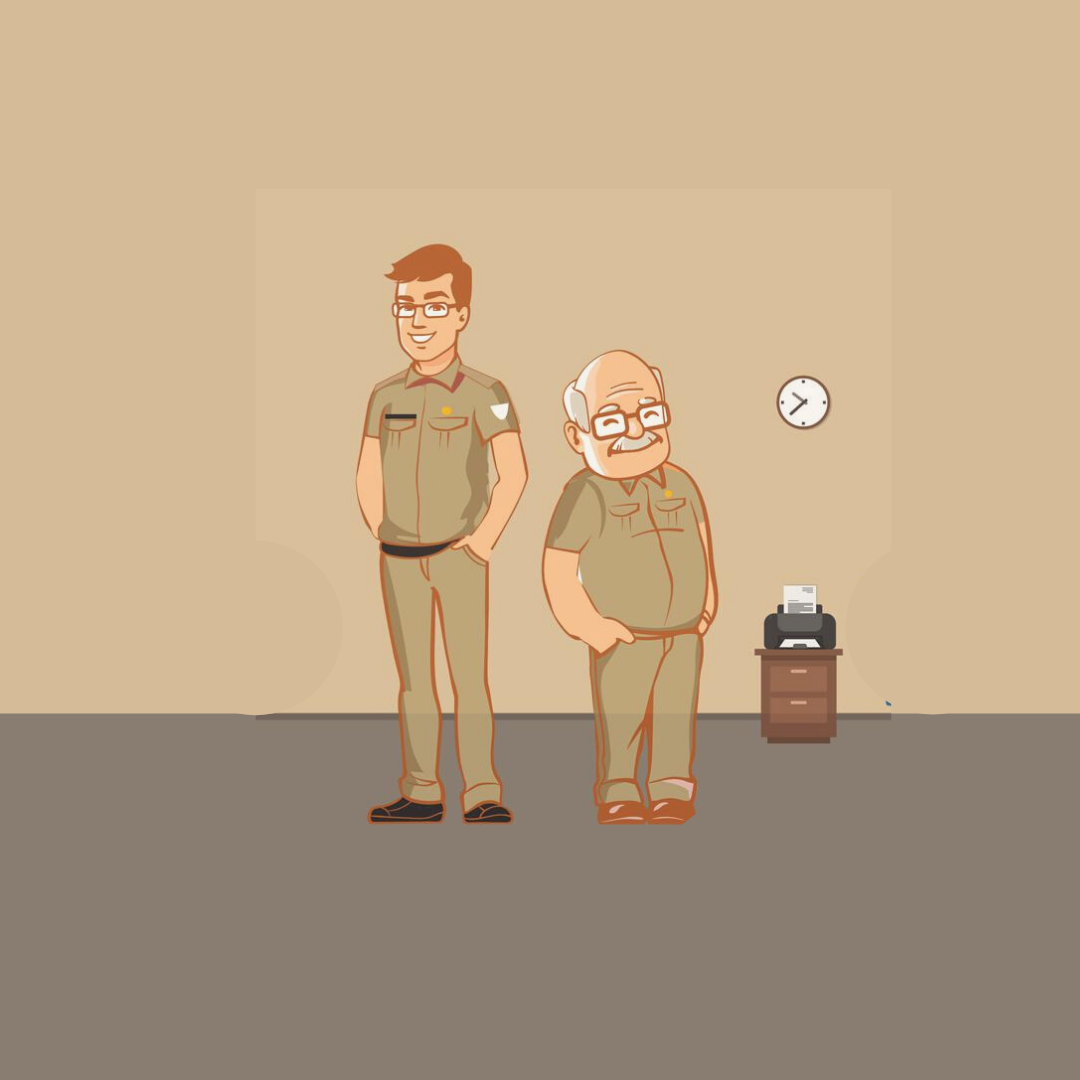

Reflektif skali. Keren lah