Dua variabel yang saya pakai sebagai judul tulisan ini sungguh sangatlah luas dan tak jelas batasannya.
“Pariwisata” dan “Kebudayaan” bersinggungan atau bertindih tepat dengan begitu banyak hal lain, baik turunan dari keduanya, maupun akar-akar yang mengerucut pada keduanya.
Pada tulisan pertama ini, saya sengaja tidak menyebutkan sub-judul apa yang kiranya menjadi fokus yang akan saya teliti atau bahas.
Hal ini saya maksudkan agar mula-mula, baiklah (sekali lagi) saya memberi sebuah gambaran umum mengenai “Pariwisata” dan “Kebudayaan”. Sebuah pemahaman dasar tentang kedua entitas ini, saya kira perlu terlebih dahulu dibentangkan.
Harapan kita, tulisan ini–yang tentu saja tidak merangkum semua versi–akan berkembang, selanjutnya. Saya juga sudah memikirkan tentang bagaimana kedua variabel ini mesti dirincikan sesuai konteks, tempat atau locus tertentu, juga kebutuhan yang lebih mendesak lainnya.
Kali ini saya mulai secara teoretis, semacam sebuah studi literer. Sehingga, bolehlah saya menantang diri saya sendiri dengan membuat proyek ini–meski hanya melalui tulisan–berkelanjutan, dan pada giliranya menemukan sasarannya yang lebih nyata.
Pariwisata
Dalam temuannya, H. Oka A. Yoeti menyebutkan bahwa kata “Pariwisata” sesungguhnya baru populer di Indonesia setelah Musyawarah Kedua Nasional Tourisme digelar di Tretes, Jawa Timur, pada 12-14 Juni 1958.
Sebelumnya, digunakan istilah “Tourisme” yang berasal dari Bahasa Belanda untuk menyebutkan segala hal-ihwal yang hingga detik ini kita mengerti sebagai “Pariwisata” itu.
Dalam amanatnya waktu itu di Gedung Pemuda, Surabaya, Presiden Soekarno bertanya kepada Menteri P dan K, Prof. Prijono, mengenai kata Bahasa Indonesia apa yang tepat menggantikan “Tourisme”.
Prof. Prijono kemudian menjawab, ada dua. Pertama, “Dharmawisata” untuk perjalanan antarkota (dalam negeri). Kedua, “Pariwisata” untuk perjalanan antarbenua (luar negeri).
Waktu itu, “Tourisme” resmi diganti menjadi “Pariwisata” oleh Bung Karno sendiri. Atas dasar ini, pada tahun 1960, Dewan Tourisme Indonesia diubah menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (DEPARI).
Baca Juga: E-tourism dan Pembangunan Pariwisata di NTT
Jenderal G. P. H. Djatikusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata, punya andil penting dalam mensosialisasikan istilah ini.
Di sini, saya melihat sesuatu yang sangat visioner-progresif, sesuatu yang lintas-batas, dalam keputusan Bung Karno itu.
Cukup gunakan “Pariwisata” yang terus dipakai hingga kini, dalam artian, segala sesuatu yang mestinya berada dalam cakupan “Dharmawisata”, dijalankan sesuai standar internasional, sebagaimana “Pariwisata” menurut Prof. Prijono tesebut di atas.
Dalam logikannya yang paling sederhana, apabila jawaban Prof. Prijono ini dipakai secara radikal, saya kira siapa saja yang kini berkecimpung dalam dunia, dalam lembaga, dalam gerakan, dalam komunitas, dalam institusi, atau dalam dinas kepemerintahan, mesti sekurang-kurangnya paham dan fasih menggunakan minimal satu bahasa asing.
Kenyataannya, harapan ini tampaknya tidak terlalu menggembirakan.
Sebelumnya, para ahli–untuk menyebut beberapa–membuat batasan atas dan/atau tentang “Pariwisata”.
Hermann V. Schulard (1910), seorang ahli ekonomi Austria, mendefinisikan “Pariwisata” sebagai “sejumlah kegiatan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk kota, suatu daerah atau suatu bangsa” .
Karena dibuat oleh seorang ahli ekonomi, “Pariwisata” akhirnya menjadi sangat ekonomi-sentris. Aspek-aspek lain semisal sosial, psikologi, seni, budaya, maupun geografi, kurang mendapat tempat.
Namun, bukan tidak ada, hari-hari ini, “Pariwisata” juga digenjot habis-habisan hanya dan hanya untuk tujuan profit semata.
Guyer Freuler membuat rumusannya sendiri. “Pariwisata” dalam artian modern merupakan “fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar akan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan” . Freuler lebih luas memandang “Pariwisata” ketimbang Schulard
Batasan yang lebih teknis dikemukakan oleh Prof. Hunzieker dan Prof. K. Krapf (1942). Kepariwistaan adalah “keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu” .
Meski definisi ini diterima secara resmi oleh The Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST) dan berlaku hingga kini, bagian “.. tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu” itu, hemat saya, agaknya masih bisa diperdebatkan.
Kebudayaan
Sepintas lalu, kita tahu apa itu “Kebudayaan”, tetapi akan menjadi agak lama dan tak jelas jawabannya, ketika seseorang bertanya secara serius pada kita, “Apa itu kebudayaan?”.
“Kebudayaan” merupakan suatu entitas otonom dalam totalitas kehidupan manusia. Faktor-faktor lain semisal konstelasi sosial atau kosmologi turut pula memengaruhinya.
Ada dua pandangan fundamental mengenai apa yang disebut sebagai “komponen pokok Kebudayaan” .
Pertama, pandangan bahwa “Kebudayaan” par excellence merupakan nilai-nilai budaya beserta segala hasil pemikiran manusia dalam suatu masyarakat, sedangkan tingkah laku dan benda-benda hanyalah ikutan darinya.
Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa “Kebudayaan” merupakan keseluruhan hasil pemikiran, pola tingkah laku, maupun benda-benda hasil karya manusia.
Mengenai apa yang disebut sebagai “inti budaya” pun, ada dua persepsi yang kontradiktif (ibid). Teori idealistik menyatakan bahwa pembentukan “Kebudayaan” ditentukan oleh kapasitas manusia yang dapat menciptakan dan mengembangkan ide-ide.
Sedangkan teori materialistik menyatakan bahwa pembentukan “Kebudayaan” ditentukan oleh lingkungan alam dan peluang ekonomi (alam materi) yang dihadapi manusia dalam kesehariannya.
Nilai-nilai budaya yang dianggap baik, luhur, dan berguna, selanjutnya diinternalisasi melalui pelbagai macam program belajar.
Ada yang terstruktur ke dalam kurikulum formal, ada yang diwariskan secara informal dan non-formal (meneruskan tradisi, mengikuti adat-istiadat).
Dalam pengertian inilah, para Penjasa Republik ini melihat adanya kesalingterkaitan yang erat antara Pendidikan dan “Kebudayaan”. Itulah mengapa, sebelum diganti, kita punya satu kementerian, Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pariwisata dan Kebudayaan
Sebagai akhir, sebuah pertanyaan strategis lagi kontekstual dapat diajukan. Bagaimana relasi yang proporsional antara “Pariwisata” dan “Kebudayaan”?.
Atau, bagaimana “Pariwisata” memengaruhi “Kebudayaan”? Atau, bagaimana “Kebudayaan” turut berkontribusi bagi perkembangan “Pariwisata”?.
Atau, bagaimana membangun “Pariwisata” yang berbasiskan “Kebudayaan”?.
Atau, bagaimana mengembangankan “Kebudayaan” yang pada gilirannya berimbas pada “Pariwisata”
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat masing-masing kita jawab. Bila ditanyakan pada saya, maka saya akan menjawabnya dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Tulisan-tulisan lanjutan dari apa yang baru selesai Anda baca ini.
*) Gagasan kolumnis ini adalah sepenuhnya tanggungjawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi
Baca juga tulisan lain di kolom Gagasan atau tulisan menarik lainnya dari Reinard L. Meo

Oleh: Reinard L. Meo


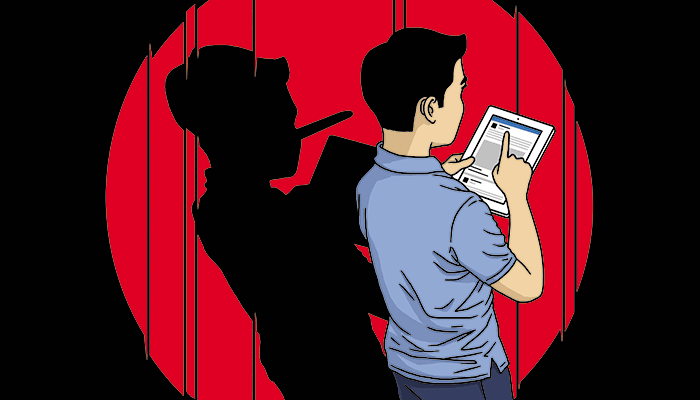

Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.