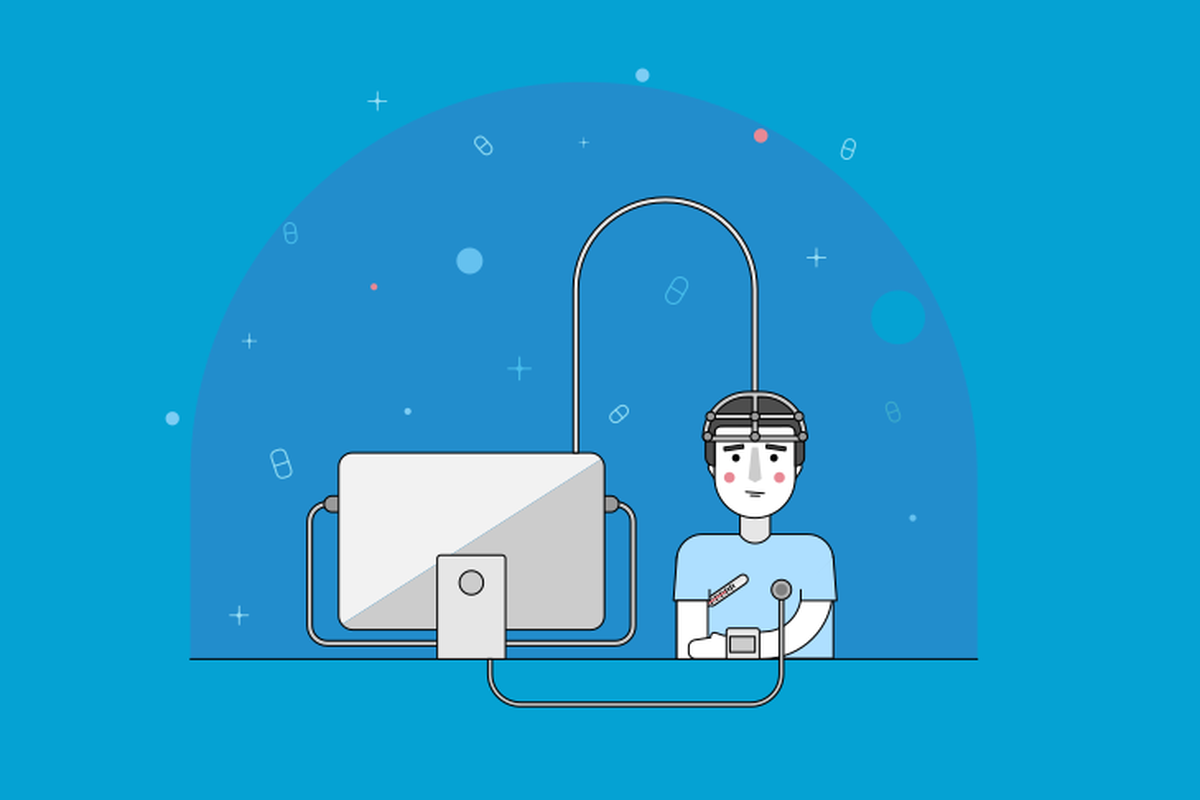“Orang lebih mau menyembunyikan kalau dia kena covid. Karena orang sudah punya stigma negatif. Orang kalau kena covid, masuk rumah sakit, mati, Fatukoa.”
Saya mendengarnya dari seorang ibu di Maulafa, Kota Kupang. Saat itu kami sedang bercerita seputar pengalamannya merawat anak yang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Menurut dia, sebagian besar orang enggan ke rumah sakit karena takut nantinya berakhir di Fatukoa.
Fatukoa merupakan wilayah kelurahan yang menjadi lokasi penguburan pasien COVID-19 di Kota Kupang. Nama resminya Tempat Pemakaman Umum (TPU) Damai. Tapi dalam percakapan sehari-hari, orang sudah terbiasa menyebutnya TPU Fatukoa. Bahkan hanya menyebut nama “Fatukoa” saja, bayang-bayang seram dalam benak mulai bersemayam.
Bagi pembaca dari luar Kota Kupang, Anda bisa menyesuaikan nama lokasi TPU khusus pasien COVID-19 itu. Apapun namanya, pasti menyisakan trauma bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan orang lain yang hanya menyimak dari berita pun ikutan takut.
Saking takutnya, setiap orang akan berusaha bagaimana caranya supaya dirinya atau keluarganya tidak ada yang berakhir di sana. Maka mulailah mereka merunut, kenapa orang tidak bisa mengelak dari “takdir” Fatukoa?
Berdasarkan kajian ala kadarnya, mereka menemukan sebuah pola. Setiap orang yang divonis COVID-19 di rumah sakit, tidak boleh ada lagi keluarga yang berkunjung. Kalau sampai meninggal dunia, maka tidak bisa disemayamkan di rumah tapi langsung dikuburkan oleh petugas di Fatukoa.
Dari pola tersebut, sebuah kesimpulan sederhana dan agak serampangan pun dibuat: kalau ada keluarga yang sakit, jangan sampai cari pertolongan ke rumah sakit. Rawat sendiri di rumah saja. Hindari berurusan dengan petugas kesehatan, gugus tugas atau apapun namanya yang berasal dari pemerintah.
Kenapa respons seperti itu bisa terjadi? Apakah keputusan tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan selama pandemi COVID-19 itu baik dan aman? Dua pertanyaan mendasar itulah yang menjadi inti ulasan Pojok Sehat kali ini.
Ritual Kematian yang Berubah
Setiap orang memang akan meninggal dunia pada waktunya. Kita selalu diingatkan dengan kalimat penghiburan semacam itu dalam acara kedukaan. Tapi, ketika cara meninggal dan memperlakukan orang meninggal dianggap tidak wajar, hal itu tidak bisa diterima begitu saja dan akan menyisakan trauma.
Sebagai orang berbudaya dan beragama, setiap daerah atau suku tertentu pasti memiliki ritual kematian yang unik. Di Manggarai, misalnya, ritual adat kematian dimulai dengan upacara haeng nai, wero mata, tekang tana dan akan berakhir pada acara kelas atau pesta kenduri.
Apapun model ritualnya, pada umumnya dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir pada orang yang meninggal sebelum dimakamkan. Ritual kematian ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan dipraktikkan sepanjang waktu hingga saat ini.
Tapi, kondisi pandemi COVID-19 membuat semua kebiasaan itu—mau tidak mau—berubah. Setiap pasien COVID-19 yang meninggal dunia akan diperlakukan secara khusus, sesuai panduan yang direkomendasikan WHO. Intinya, prosedur tersebut memangkas beberapa ritual kematian yang penting.
Baca Juga: Jangan Ragukan Vaksin
Penanganan jenazah COVID-19 sesuai protokol WHO itu bertujuan untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 pada orang lain yang masih sehat. Sebab meskipun orangnya sudah meninggal dunia, virus penyebab COVID-19 itu masih bertahan lama.
Perubahan ritual kematian selama pandemi COVID-19 menjadi keluhan semua masyarakat dunia. Orang Amerika yang dianggap lebih modern juga ikut menyambat dengan proses pemakaman jenazah COVID-19 yang dianggap kurang manusiawi.
Apalagi kita di Indonesia, kasus perebutan jenazah COVID-19 terjadi di berbagai daerah, termasuk beberapa kali terjadi di Kupang dan daerah lain di NTT. Tidak semua orang bisa menerima ketentuan penanganan jenazah COVID-19 tersebut, apalagi tidak ditopang cara komunikasi yang baik dan adanya perlakukan yang berbeda bagi pejabat tertentu.
Namun di sisi lain, tindakan pengambilan paksa jenazah COVID-19 dari petugas kesehatan dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga bisa mendapatkan sanksi pidana. Itulah mengapa beberapa keluarga yang sudah mengambil jenazah secara paksa, pada akhirnya menyerah dan minta maaf kepada publik.
Situasinya memang sangat dilematis. Mau ikuti aturan, kita dirundung perasaan bersalah karena tidak menjalankan ritual kematian. Mau membangkang dari aturan, ancaman hukum membuat tidak banyak berkutik.
Buntutnya terjadi hubungan yang renggang antara masyarakat dengan unsur pemerintah. Mungkin tidak hanya renggang, tapi sudah ada rasa tidak percaya sama sekali. Salah satu indikatornya terlihat dari anjuran untuk tidak perlu ke rumah sakit bisa sedang sakit sebagaimana digambarkan pada awal tulisan ini.
Membangun Hubungan Harmonis
Bila kita merunut kembali ke belakang, respons masyarakat yang berubah memunggungi fasilitas kesehatan bukan tanpa sebab. Sebagian besar orang kecewa dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
Memang benar, penanganan COVID-19 itu harus sesuai standar. Namun, pendekatan yang diberikan harus bersifat humanis dan peka budaya, sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Karena itu, pemerintah—tenaga kesehatan atau gugus tugas penanganan COVID-19—perlu mengevalusi metode yang telah diterapkan selama ini.
Bagi sebagian orang yang terlanjur memiliki persepsi buruk pada layanan kesehatan, sebaiknya berpikir ulang. Barangkali citra buruk itu terjadi akibat perilaku satu dua oknum saja, sehingga tidak adil bila kita menganggap semua faskes itu sama saja.
Penanganan COVID-19 di Indonesia memang menganjurkan penderita yang tanpa gejala atau bergejala ringan untuk menjalani isolasi mandiri. Meski ada kata “mandiri” di sana, kita tetap membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pelayanan kesehatan.
Kita perlu bersyukur, saat ini layanan konsultasi kesehatan secara daring sudah tersedia. Sehingga, meski kita menjalani isolasi mandiri di rumah, kita tetap bisa menghubungi tenaga kesehatan untuk menanyakan berbagai hal terkait gejala atau penanganan sederhana yang bisa dilakukan di rumah.
Layanan telemidisin itu beragam. Di Kota Kupang, misalnya, sudah tersedia layanan Telekonseling Terapi Isoman. Pemkot menyebarkan nomor tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai wilayah kelurahan, sehingga mudah dihubungi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Jika tanda dan gejala terasa makin memburuk, kita tidak mungkin bertahan di rumah terus. Kita perlu mengabarkan ke petugas kesehatan terdekat lewat telekonseling tadi, sehingga bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Layanan seperti ini di Kota Kupang biasanya berkolaborasi dengan tim Brigade Kupang Sehat (BKS).
Setiap layanan kesehatan memang tidak 100% menjanjikan kesembuhan. Namun, kita bisa melihat angka kesembuhan pasien COVID-19 juga cukup tinggi dari waktu ke waktu. Artinya, harapan untuk sembuh itu selalu ada. Karena itu, ada baiknya kita mengembangkan sikap optimisme selama mencari bantuan pengobatan ke fasilitas kesehatan.
Tapi, bagaimana kalau di rumah sakit malah meninggal dunia? Bagaimana kalau jenazahnya harus berakhir di Fatukoa? Bagaimana kalau begini…, bagaimana kalau begitu?
Yah, kalau hidup kita selalu terkungkung dalam bayang-bayang “Fatukoa”, apapun tawaran solusi yang ada tidak ada gunanya. Hidup dalam bayang-bayang “Fatukoa” akan baik jika hal itu mendoroang kita makin patuh pada protokol kesehatan.

Oleh: Saverinus Suhardin
Baca juga tulisan lain di kolom Pojok Sehat atau tulisan menarik lainnya dari Saverinus Suhardin