Judul: Di Kaki Ina Bo’i
Penulis: Sipri Senda
Penerbit: Perkumpulan Komunitas Sastra Dusun Flobamora
Cetakan: 978-623-91779-04
ISBN: 0140442103 (ISBN13: 9780140442106)
***
Di puncak gedung rakyat
Mimpi jiwa-jiwa melarat
Bertebaran diterjang musim barat
Hilang rupa dan kini sekarat
Di tikungan perselingkuhan pengusaha-pejabat
Cerita derita miskin tak pernah tamat
Koran-koran terus mencatat
Dan menjadi ampas di kaki pelaknat
(Bait kedua, puisi “Di Kaki Ina Bo’I”)
Demikianlah salah satu kutipan bait dari puisi “Di Kaki Ina Bo’I” (DKIB) karya Sipri Senda. Puisi ini jelas menujukkan kritik terhadap realitas sosio-politik yang korup.
Sebagai judul yang dipilih untuk menamai kumpulan puisi ini, nada dasar tematik yang dominan dalam puisi ini kiranya menjadi fenomen umum gaya ucap Sipri Senda dalam menyampaikan puisi-puisinya.
Ulasan ini akan bergerak dari pengamatan fenomen umum gaya ucap Sipri Senda yang berkiblat pada–apa yang saya namakan–puisi kritis-profetis.
Term “kritis-profetis” merujuk pada konsep kritik sebagai upaya aktif akal budi untuk melawan pelbagai ketimpangan yang dilekatkan dengan konsep “profetis” atau kenabian.
Sebagai seorang pastor, posisi berpikir kritis melekat pada tuntutan panggilan kenabian untuk menyerukan kebenaran. Dengan kata lain, kebenaran menjadi titik gravitasi yang menarik semua refleksi Sipri Senda yang kemudian diucapkan dalam puisi-puisinya.
Kumpulan Puisi DKIB ini merangkum 62 puisi yang ditulis dalam rentang waktu yang cukup panjang.
Keenam puluh dua puisi ini memang secara tematik merangkum beberapa tema, seperti: sosial-politik, religiositas, persahaban, dan cinta. Namun, tema-tema ini digerakkan dengan daya gerak yang sama, yakni kritik (profetik).
Alih-alih Sipri Senda melakukan mimesis (penyalinan/imitasi) terhadap realitas. Ia berbicara dengan posisi antitesis.
Perlawanan reflektif ini membuka ruang kesadaran pembaca untuk keluar dari pseudo-kenyamanan (kenyamanan semu) yang telanjur mengeras dalam ruang publik.
Realitas korupsi, janji-janji palsu politik, moralitas publik, bahkan kesadaran semu religiositas ditempatkan sebagai objek untuk dilawan dalam puisi.
Untuk itu, jelas puisi-puisi Sipri Senda bergerak pada ranah puisi realisme dengan gaya ucap kritis-profetis yang lugas dan langsung.
Sipri Senda mengkritisi gejala kapitalisme yang menjadikan derajat manusia direduksi sampai pada level “barang atau benda”.
Dalam puisi “You are Nothing”, Sipri menulis: Silently/ Standing applause you smile to the moon/ And your panties are opened one by one/ On this altar of capitalism/ Your life is offered/ In the name of nothing// Sintus Runesi, yang memberikan prolog kumpulan puisi DKIB ini mengomentari puisi ini demikian: “Sajak ini mengingatkan saya pada lamentasi Hokheimer dan Adorno dalam karya mereka, Dialectic of Enlightenment.
Dalam buku ini keduanya menulis bahwa dalam kerangka maksimalisasi keuntungan, kemanusiaan kita, ketimbang bergerak menuju keadaan yang lebih baik, malah terjerembab masuk ke dalam sebentuk barbarisme baru.
Dalam barbarisme ini, kebalikan dari animisme yang mengisi objek-objek material dengan jiwa, kapitalisme mengubah jiwa-jiwa menjadi barang atau benda.” Melalui puisi ini, Sipri Senda menegaskan perlawanan terhadap kapitalisme yang mereduksi “your life” menjadi “nothing.”
Moralitas buruk yang melekat ad personam pada oknum pejabat juga dikritik dengan lugas dan tajam dalam puisi “Pejabat Puber”. “Kau membawaku ke pantai/ Berselingkuh di perut perahu karam/ Kutatap bintang di matamu/ Terbaca mimpi–mimpi liar dari hasrat paling purba/ Kau meracau dengan geletar tubuhmu menyatu gelombang laut/ Hmmmmm di saat seperti ini/ Ternyata pejabat seperti dirimu tak ubah remaja puber//” (bait kedua).
Nuansa profetik sebagai bentuk kritik kenabian muncul dalam opsi mendasar untuk mengambil posisi solider dengan sesama yang tertindas dan miskin. Bahasa teologis mengatakan opsi ini dengan istilah “preferential option for the poor”; Sebuah opsi preferensial terhadap kaum miskin (yang tertindas). Sipri mengangkat narasi the poor (kaum miskin) sebagai tanda keberpihakannya melalui gaya ucap yang menyentil kesadaran.
Bahasa teologis mengatakan opsi ini dengan istilah “preferential option for the poor”; Sebuah opsi preferensial terhadap kaum miskin (yang tertindas). Sipri mengangkat narasi the poor (kaum miskin) sebagai tanda keberpihakannya melalui gaya ucap yang menyentil kesadaran.
Pada penggalan puisi “Jalan Setapak”, Sipri menulis “Ina e, ini malam ketong makan apa?”/ “Ama e, ini malam ketong puasa lai e…” (Baris ke-4 dan ke-5, Bait ke-3).
Pada puisi-puisi dengan aroma khas pengalaman religius, Sipri Senda memosisikan diri dalam posisi inferior terhadap kekuasan Allah yang menggetarkan (tremendum) namun sekaligus mempesona (fascinans).
Berbeda dengan posisi refleksi berhadapan dengan realitas sosial dalam tataran relasi horizontal, pada puisi-puisi religius, Sipri tidak menunjukkan bentuk “perlawanan reflektif” untuk menantang ekses buruk beragama yang keliru.
Ia memosisikan diri dalam ketaatan dan inferioritas kebatinan. Kritik malah ia tarik ad intra; ke dalam dirinya sendiri.
Baca Juga: Merayakan Inkarnasi dalam Puisi
Dalam puisi “Di Depan Bunda”, Sipri menulis: “Di depan Bunda/ Kutunduk malu-malu/ Tak dapat kusembunyikan mukaku/ Belepotan lumpur dusta dosa/” Pada penggalan puisi “Ibadah” pun Sipri menunjukkan dimensi penyesalan yang menyimbolkan jarak antara Allah yang Maha Benar dan aku lirik yang berdosa. “Atas nama pertobatan/ Kutoreh tanda salib dengan warna pasrah// (Baris ke-6 dan ke-7, bait ke-2).
Ada kekhasan muncul pada beberapa puisi yang mengkritik ketimpangan sosial dengan gaya ucap lokal Kupang. Misalnya, pada puisi “Kupang”, Sipri mengkritik kontestasi suhu politik yang lebih banyak menimbulkan perpecahan sembari mengangkat realitas kemiskinan melalui tokoh “Ana kici penjual koran.”
Pada puisi “Ama Dope” pun tersirat kritik terhadap kesenjangan sosial dengan perilaku bobrok “orang berada/ penguasa” yang diimpresi oleh aktus membuang kulit pisang yang dilakukan oleh seorang pengendara “oto fortuner.” Sedang di sisi yang lain, perlawanan orang-orang kecil yang direpresentasikan oleh “makian Ama Dope” malah dianggap lelucon oleh orang banyak. Dengan kata lain, suara orang lemah (voiceless) tidak pernah dianggap serius dalam ruang publik.
Sebagai suatu kumpulan puisi, kehadiran DKIB karya Sipri Senda ini patut diapresiasi, apalagi puisi-puisinya hadir untuk membuka ruang kesadaran pembaca terhadap realitas ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, sebagai sebuah karya, tentu ada pula titik-titik lemah yang perlu menjadi catatan reflektif bagi penyair. Apalagi, dalam konteks puisi berkiblat kritis-profetis, tentu merangkum dalam dirinya suatu daya keterbukaan terhadap kritik. Jika tidak, ia gagal sebagai pesan kritik.
Risiko terbesar dari menulis puisi-puisi realisme dengan gaya ucap kritik yang lugas dan langsung adalah terbebannya puisi dengan jejal makna yang–jika tidak diperhitungkan dengan jeli–akan menjadikan puisi kehilangan dimensi estetisnya.
Dengan kata lain, puisi bisa menjadi klise. Puisi-puisi dengan gaya seperti ini sebenarnya membutuhkan eksplorasi ketat imaji dan keterampilan mempelajari diksi yang lebih kaya. Hal ini dapat menyelamatkan puisi-puisi dengan pengungkapan yang mirip.
Baca Juga: Tuhan a la Cyprian
Kemampuan abstraksi untuk menyaring emosi dan “kemarahan” sehingga tidak melumer dalam setiap kata pada puisi juga dapat memberikan alternatif dalam mengolah suasana batin puisi.
Namun, terlepas dari semua catatan kritis ini, buku puisi DKIB ini telah memberikan warna tersendiri dalam peta perkembangan sastra di NTT yang masih tergolong minim dalam upaya publikasi.
Saya pikir, eksplorasi puisi dengan gaya ucap lokal ternyata hadir dengan lebih luwes dan memiliki dimensi satirik yang cukup kuat untuk mengkritik ketimpangan sosial.
Ketekunan untuk tidak pernah sampai pada titik “selesai” dalam menciptakan puisi adalah jalan keselamatan bagi proses kreatif seorang penyair. Selamat membaca!

Oleh: Giovanni A. L Arum
Baca juga tulisan lain di kolom Resensi atau tulisan menarik lainnya dari Giovanni A. L Arum




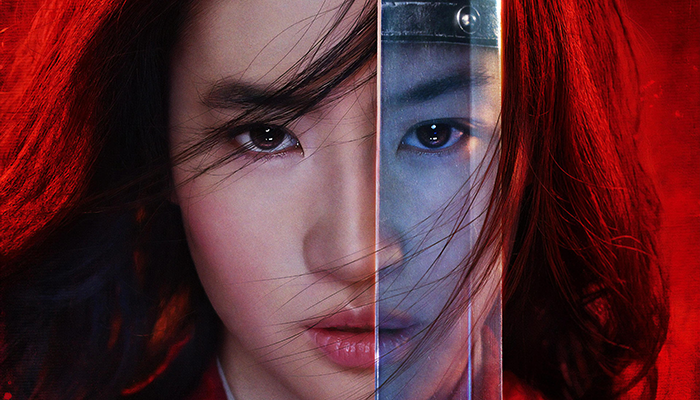
Mantap Ka Aditia, saya suka bagian akhirnya, “Ketekunan untuk tidak pernah sampai pada titik ‘selesai’ dalam menciptakan puisi adalah jalan keselamatan bagi proses kreatif seorang penyair.”
Mantap Ka Aditia, saya suka bagian akhirnya, “ketekunan untuk tidak pernah sampai pada titik ‘selesai’ dalam menciptakan puisi adalah jalan keselamatan bagi proses kreatif seorang penyair.” Salve.
“Ketekunan untuk tidak pernah sampai pada titik “selesai…..”
Dalam arti, puisi identik dengan bisikan suci dari dalam hati yang menggerakkan naluri untuk menulis. Berhenti menulis artinya “selesai” . Berhenti berpuisi, berhenti menulis berarti mati.