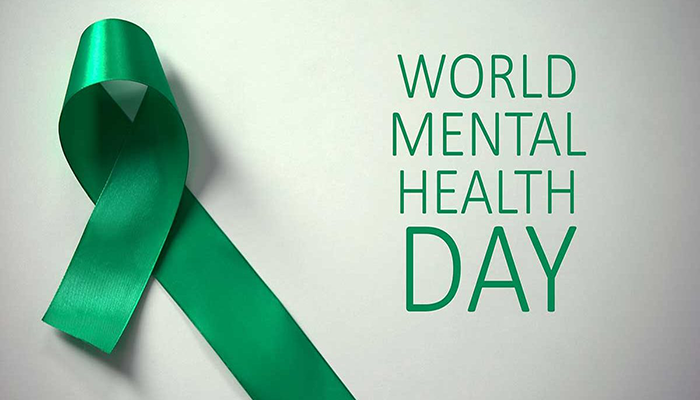Apa yang kamu rasakan ketika mendengar bunyi sirene ambulans?
Barangkali kita merasa biasa saja; hanya sebagai pengingat agar segera menepi bila kendaraan kita berada di depan ambulans yang sedang meraung-raung itu, tapi bagi beberapa orang bisa jadi hal itu membangkitkan kenangan trauma tertentu.
Seperti dialami salah satu keluarga penyintas COVID-19 yang berdomisili di bilangan Naikoten, Kota Kupang, NTT. Bagi mereka bunyi sirene itu sangat traumatis, karena menjadi tanda perpisahan dengan orang yang sangat mereka cintai.
Narasi duka keluarga tersebut digambarkan dalam laporan penelitian kualitatif yang dilakukan Koli & Takene (2021). Kedua peneliti itu memperoleh cerita dari salah satu Pendeta GMIT yang mendampingi keluarga tersebut selama dinyatakan positif COVID-19.
Mereka keluarga kecil, terdiri atas sepasang suami istri dengan dua orang anak. Pendapatan mereka sehari-hari diperoleh dari aktivitas berjualan sayur dan barang kebutuhan dasar lain di Pasar Naikoten.
Ketika suami menderita sakit dan dinyatakan positif COVID-19, satu-satunya sumber ekonomi itu lumpuh total. Mereka dijauhkan oleh pembeli dan warga sekitar. Selain itu, pikiran keluarga banyak terkuras pada urusan kesembuhan suami atau ayah mereka.
Ketika sudah dipastikan menderita COVID-19 saat dirawat di RST Wirasakti, keluarga syok dan makin tertekan, sampai-sampai anak sulung mereka jatuh pingsan. Semenjak saat itu, keluarga tidak bisa lagi mendampingi suami atau ayah mereka secara langsung.
Perasaan keluarga makin kalut ketika mendapat kabar kondisi suami atau ayah mereka makin memburuk, dan harus dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Johannes, Kupang. Mereka tidak punya harapan lagi untuk berjumpa. Sehari kemudian, bagaikan sambaran petir di siang bolong, mereka mendapat kabar duka.
Ketika dikabarkan sudah meninggal dunia, keluarga tetap tidak diizinkan datang melihat jenazahnya. Mereka tidak bisa memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum atau prosesi lain sebagaimana lazim dilakukan ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Mereka merasa ditinggalkan begitu saja.
Kabar duka itu terjadi pada malam hari. Saat itu Ibu Pendeta yang mendampingi keluarga tersebut sempat menelepon istri almarhum. Hanya terdengar jeritan tangisan dari seberang, lalu Ibu Pendeta mendengar suara terbata-bata, “Mama, mama, dong su tolak (bawa) bapa, kotong sonde boleh mendekat, hanya lihat dari jauh.”
Semua urusan penguburan dilakukan oleh petugas. Keluarga hanya bisa menebak suami atau ayah mereka sudah dikuburkan dari bunyi sirene ambulans yang melaju kencang ke arah Fatukoa.
Setelah itu, Ibu Pendeta berusaha menghubungi lagi via telepon, tapi tidak tersambung. Menurut keterangan tetangga, ibu dan kedua anaknya melewati malam paling berduka itu di rumah—hanya bertiga saja. Kondisi rumah gelap, tapi dari sana terdengar ratapan yang menyayat hati.
Keesokan harinya, keluarga mengabarkan kepada Pendeta kalau mereka bertiga juga tekonfirmasi positif COVID-19, dan harus segera menjalani perawatan dengan pemantauan ketat di rumah sakit.
Semenjak saat itu, keluarga tersebut tidak hanya trauma dengan sirene ambulans. Mereka juga merasa tatkut berurusan dengan rumah sakit; sangat sensitif dengan stigma “keluarga terpapar COVID-19”; dan mulai timbul penyangkalan akan adanya wabah tersebut.
Masalah Kesehatan Jiwa
Sejak awal kemunculan SARS-CoV-2, hampir tidak ada yang membatah kalau virus varian baru penyebab COVID-19 itu tidak hanya menggerogoti manusia secara fisik, tapi juga ikut mengganggu secara psikologis. Pandemi COVID-19 telah memberi dampak yang sangat signifikan pada masalah kesehatan mental.
Laporan mengenai jenis dan jumlah gangguan mental akibat wabah tersebut bervariatif dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Mulai dari bergejala ringan seperti kecemasan yang menyebabkan gangguan tidur, hingga kondisi depresi yang memicu aksi bunuh diri.
Setiap orang atau keluarga tentunya melewati pengalaman yang berbeda. Gambaran kasus yang terjadi pada salah satu keluarga di Naikoten, Kupang yang digambarkan di awal, benar-benar mengganggu pikiran dan perasaan. Dampak psikologis dari pandemi COVID-19 itu nyata dan terasa sangat kompleks.
Kita tentu mengakui, masalah kejiwaan memang sudah ada jauh sebelum wabah COVID-19 itu merebak. Pendek kata, selama kita masih hidup, gangguan jiwa menjadi bagian yang tidak dapat terhindarkan. Bedanya mungkin hanya pada tingkatan atau berat-ringannya kondisi, tetapi yang jelas semua orang berpotensi akan mengalaminya.
Karena itu, setiap orang sebaiknya memiliki keterampilan mengelola stres. Kalau harapan itu bisa terwujud, maka kamampuan itu makin menguat jika saling mendukung dalam keluarga atau komunitas yang lebih luas. Pada kondisi tertentu yang agak berat, barulah kita mencari pertolongan tenaga profesional.
Kondisi Layanan Kesehatan Jiwa
Layanan kesehatan dasar merupakan hak asasi bagi setiap orang, termasuk untuk masalah kesehatan jiwa. Itulah konsep dasar Universal Health Coverage (UHC) yang diperjuangkan semua negara di bawah koordinasi WHO. Apakah UHC itu sudah terimplementasi dengan baik?
Secara umum masih jauh panggang dari api. Termasuk layanan kesehatan jiwa, khususnya selama pandemi COVID-19, ada begitu banyak tantangan sehingga harapan adanya kesetaraan belum bisa terwujud.
Ada kesejangan yang besar antara negara maju dan berkembang. Begitu pula variabel lain seperti ras, kondisi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak unsur lain yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan kesehatan.
Karena itu, tidak heran bila World Federation for Mental Health mengusung tema “Mental Health in an Unequal World” (Kesehatan Mental di Dunia yang Tidak Setara) dalam perayaan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober 2021. Tetapi pemerintah kita melalui Kemenkes RI merumuskan subtema nasional, “Kesetaraan dalam Kesehatan Jiwa untuk Semua.”
Kalau subtema itu merupakan pernyataan tentang kondisi saat itu, tentu saja sangat bertentangan dengan fakta di lapangan. Jika itu adalah harapan, saya merasa pesimis mimpi itu dapat segera tercapai. Karena variabel penunjang untuk menggapai tujuan tersebut belum tertata dengan baik.
Hasil kajian sistem kesehatan jiwa di Indonesia menunjukkan adanya berbagai tantangan seperti sumber daya kesehatan yang masih minim; alokasi biaya kesehatan yang masih rendah; sistem informasi kesehatan yang belum memadai; meski memiliki UU Kesehatan Jiwa tapi belum memiliki perangkat hukum di bawahnya untuk pelaksanaan UU tersebut; dan peran sektor lain dalam upaya promotif dan preventif belum terasa.
Kita di NTT bisa melihat gambaran nyata bagaimana layanan kesehatan jiwa itu belum merata dan setara. Selain masalah sumber daya kesehatan, kita juga tampaknya sudah tidak peka dengan kondisi lingkungan sekitar.
Sebagai contoh, di area jalan umum yang tidak terlalu jauh dari RSJ Naimata, kita bisa temukan banyak ODGJ yang menggelandang begitu. Mereka berada tidak jauh dari fasilitas kesehatan yang mulai beroperasi dan menambah PAD Pemprov NTT sejak tahun 2018 itu. Bagaimana nasib ODGJ lain yang berada di pulau atau daerah yang jauh?
Kalau alasannya mereka tidak ada keluarga yang mengantar dan menjamin biaya pengobatan dan perawatan di RSJ, lalu bagaimana kita bisa mengklaim sudah memberikan pelayanan yang setara? Konsep UHC yang dipelopori WHO itu harusnya tanpa alasan ini-itu, termasuk dalam urusan pembiayaan.
Masalah ketidaksetaraan lain bisa kita rasakan dalam penanganan kasus COVID-19 seperti yang dialami satu keluarga di Naikoten seperti yang diceritakan di atas. Sebab kemudian kita tahu, ketika ada pejabat mengalami masalah yang sama, kerabatnya bebas mendekat dan jenazahnya boleh dikuburkan di dekat rumah sendiri. Apakah ada kesetaraan di sana? Mimpi!
Karena itu Bapak/Ibu, Saudara/i sekalian, tidak bermaksud untuk berkhotbah, tapi sebaiknya kita memang harus kuat dan memiliki kemampuan dalam mengelola stres.
Ada banyak strategi yang bisa kita pelajari dan terapkan dalam hidup. Kita bisa memperoleh keterampilan itu dengan membaca buku atau bertanya pada orang yang kita anggap lebih mampu.
Selanjutnya kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Kita saling mendukung satu sama lain. Tunjukkan rasa cinta pada keluarga dan komunitas di sekitar kita.
Kurangi kebiasaan mengejek atau melakukan perundungan. Beri apresiasi bagi yang berprestasi. Bantu dan semangati bagi yang sedang berjuang.
Hanya dengan langkah sederhana itu kita bisa bertahan dengan kondisi hidup yang tidak baik-baik saja ini.
Perayaan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini makin menyadarkan kita bahwa masih ada: Ketidakseteraan dalam Kesehatan Jiwa untuk Semua.

Oleh: Saverinus Suhardin
Baca juga tulisan lain di kolom Pojok Sehat atau tulisan menarik lainnya dari Saverinus Suhardin