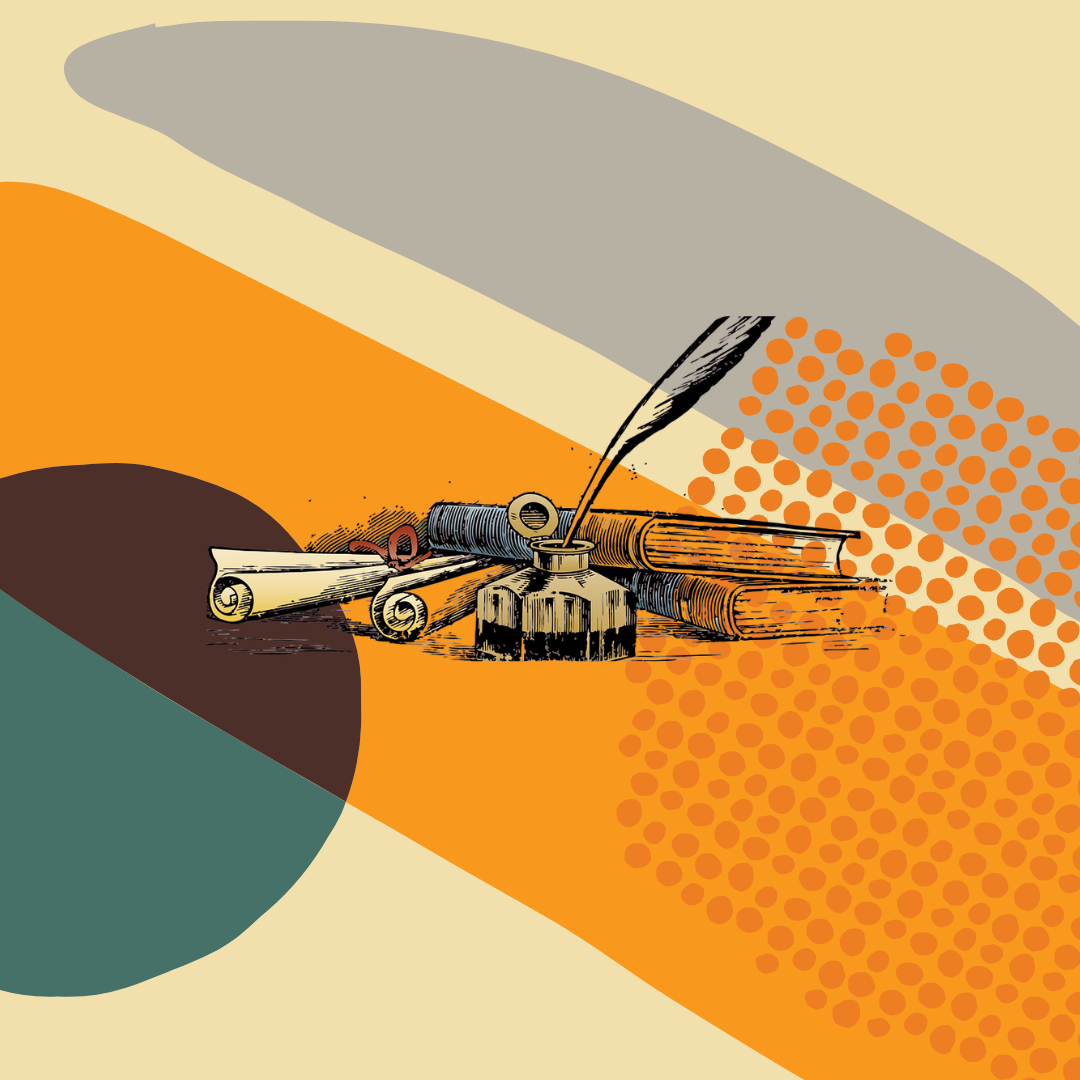“Ramadhan kali ini berbeda gara-gara korona”, ungkap sebagian orang di sekitar saya yang sedang menjalani ibadah puasa di antara kepungan korona.
Tidak bisa dipungkiri bahwa korona telah banyak membuat perubahan di bulan suci ini, mulai dari kewajiban mengenakan masker ketika beribadah, kewajiban menjaga jarak di mana-mana, hingga kewajiban mencuci tangan setiap hendak memasuki rumah ibadah meskipun tangan sudah tampak bersih .
Tak hanya itu, larangan buka bersama dengan kawan-kawan lama dan larangan mudik untuk melepas rindu terhadap keluarga sudah cukup menunjukkan bahwa Ramadhan tahun ini tak akan pernah sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jika memang Ramadhan tahun ini berbeda, maka apakah wabah ini benar-benar ‘hanya’ mendatangkan bencana dan musibah?
Tak adakah sebuah hikmah yang secara implisit terkandung di dalamnya? Bukankah setiap hal memiliki hikmah asalkan manusia mau ‘berpikir’?
Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Kalam Suci bahwa langit, bumi, dan segala isi tercipta untuk direnungi.
Urgensi pikiran dan renungan bahkan telah disinggung oleh seorang Filsuf, Rene Descartes dalam sebuah ungkapan yang berbunyi Cogito Ergo Sum-yang kira kira artinya ‘Aku berpikir, maka Aku ada’-.
Agaknya Descartes ingin mengingatkan kita—sebagai makhluk yang bergelar ‘manusia’—bahwa sebagai ciptaan kita memang ada, tetapi sebagai manusia kita belum tentu ada.
Maksudnya seperti ini: Jika kita merasa ada karena kita hidup, bernapas, bisa berjalan, dan bisa makan; maka keberadaan kita ‘hanyalah’ sebatas ciptaan—tak ada bedanya dengan singa dan sejenisnya.
Namun, Jika kita merasa ada karena kita ingin memaknai setiap jenjang kehidupan, ingin memahami setiap proses perkembangan, dan ingin menemui kebijaksanaan lewat merenung serta berpikir; maka keberadaan kita ‘layak’ disebut sebagai manusia.
Oleh sebab itu, saya ingin menunjukkan eksistensi saya sebagai seorang manusia melalui perenungan tentang hikmah dari sebuah wabah.
Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa korona telah menimbulkan kesedihan, kegelisahan, hingga kehilangan; namun bukan berarti korona tidak membawa pesan kebijaksanaan.
Dalam tulisan ini, akan diungkapkan beberapa ‘sisi lain’ dari sisi-sisi kesusahan yang kian berpilin. Saya tidak akan memaksa pembaca untuk se-iya dengan perenungan ini. Jika pembaca tidak se-iya, itu sah-sah saja. Sebab perbedaan pendapat lah yang membuat ilmu pengetahuan terus berkembang.
Kewajiban Menggunakan Masker sebagai Pesan Kehati-hatian dalam Perkataan
Masker kala korona telah menjelma sebagai ‘kebutuhan pokok’ yang sama pentingnya dengan nasi beserta saudara-saudaranya. Pemerintah juga telah dengan tegas mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan masker, tak peduli yang terjangkit maupun yang baru terbesit.
Secara eksplisit penggunaan masker bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19, namun secara implisit penggunaan masker tidak hanya sebatas itu.
Posisi masker yang berada tepat di depan mulut, menyiratkan sebuah pesan kehati-hatian dalam setiap perkataan.

Ketika seseorang menggunakan masker, keleluasaan dalam berbicara akan sedikit terhambat. Mulai dari kesulitan bernapas hingga bunyi yang keluar dengan tidak sempurna karena terhalang.
Oleh sebab itu, sudah seyogianya penggunaan masker membuat seseorang lebih pilah-pilih dalam berbicara, lebih-lebih ketika berada di rumah ibadah.
Selama ini—dulu sebelum wabah korona melanda—, bukankah beberapa kali ditemui orang-orang yang sibuk berdiskusi sendiri setelah shalat tarawih—sembari menikmati jajanan ta’jil—daripada sibuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi?
Terlepas dari susah duka korona; setidaknya lewat masker pencegahan korona, manusia mulai enggan bicara berlebihan. Selain itu, manusia juga—secara sadar atau tidak—telah mengikuti anjuran nasihat kebijaksanaan bahwa keselematan manusia bergantung dari caranya menjaga lisan.
Jaga Jarak: Menyadari bahwa Pada Akhirnya Setiap Manusia akan ‘Pergi’ Sendiri
Tak hanya ihwal masker, Pemerintah juga memberlakukan sistem jaga jarak atau physical distancing.
Lewat jaga jarak, manusia kini mulai belajar hidup secara mandiri. Jika kemarin-kemarin manusia dapat dengan mudah meminta tolong, maka kini manusia mulai ketakutan memberikan pertolongan.
Jika sebelum-sebelumnya rasa rindu selalu terus bertumbuh bagi dua keluarga yang terpisah jarak dan waktu, maka baru-baru ini rasa rindu itu telah berubah menjadi ketakutan baru terhadap bayang-bayang karantina, isolasi, bahkan kematian.
Salah satu rekan saya yang bernama Andre, warga Kedung Pengkol Surabaya harus rela dikarantina oleh keluarganya sendiri (istri, anak, dan mertua) sepulang dari kunjungannya ke Jakarta padan bulan Maret lalu.
Fakta lainnya adalah penolakan warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY terhadap lima warga pendatang dari Bandung, Jawa Barat meskipun lima warga tersebut sudah lama mengontrak di Desa Sumbermulyo.
Fakta-fakta ini akan membuat kita menyadari bahwa pada akhirnya setiap manusia akan ‘pergi’ sendiri. Terlalu bergantung pada sesama—yang sama takutnya terhadap kemiskinan dan kematian—bisa berujung penyesalan.
Oleh sebab itu, jaga jarak setidaknya mengajarkan manusia tentang kemandirian dan kesiapan diri menghadapi kepergian yang lebih abadi.
Cuci Tangan Adalah Lambang tentang Kekuasaan yang Sering Disalahgunakan
Hal terakhir yang akan direnungi lewat tulisan ini adalah kewajiban mencuci tangan dengan sabun untuk membunuh Si Virus.
Pasca melakukan aktivitas atau bersentuhan dengan sesuatu, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Tak peduli tangan kita lebih harum puluhan kali lipat dari minyak kasturi sekali pun.
Cuci tangan tidak hanya perihal menjaga kebersihan dan kesehatan, tetapi juga sebagai lambang atas kesadaran terhadap kekuasaan yang kerap disalahgunakan.
Tangan adalah simbol kekuasaan, kemampuan, dan kepemilikan. Mencucinya adalah wujud pengakuan bahwa kita sering lalai dalam menggunakan kekuasaan, memberdayakan kemampuan, dan dalam memanfaatkan kepemilikan.
Baca Juga: Covid-19 Menghampiri, Kita Perlu Tahu Cara Perawatan Mandiri
Lewat tangan, manusia sering lalai dalam memberikan tanda tangan demi sebuah keuntungan. Lewat tangan, manusia sering acuh dalam mengunduh beberapa tugas orang lain lewat internet, lalu dengan wajah tanpa dosa menerapkan SalTem—Salin lalu Tempel—yang kemudian diakui sebagai miliknya dan yang lebih menyedihkan adalah mereka justru ‘bangga’.
Lewat tangan, manusia sering lupa dalam menyisihkan sebagian miliknya untuk mereka yang memiliki hak atas itu.
Memang benar, sejak dulu seharusnya manusia sudah sering mencuci tangan, agar mereka sadar bahwa dalam beberapa detik saja, tangannya sudah penuh dengan kotoran.
 Oleh: Akhmad Idris
Oleh: Akhmad Idris
Baca juga tulisan lain di kolom Corak atau tulisan menarik lainnya dari Akhmad Idris