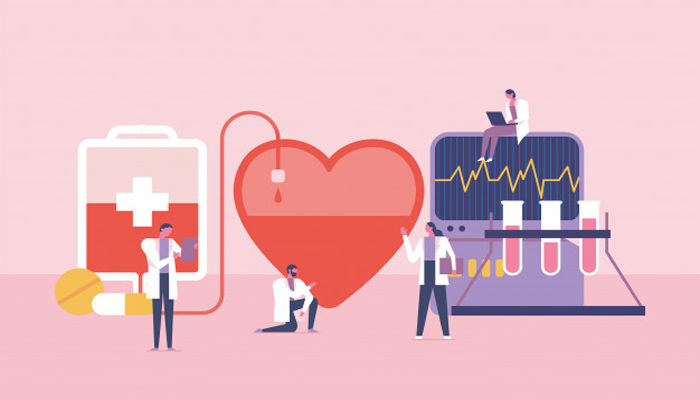Laporan resmi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi NTT menyebutkan jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di wilayah kerjanya dalam rentang waktu tahun 1997 hingga April 2020, mencapai 7.032 orang.
Dari angka tersebut, hanya 2.396 ODHA yang menjalani pengobatan antiretroviral (ARV).
Padahal, meskipun tidak mampu menghilangkan virus HIV secara total, terapi ARV telah terbukti efektif meningkatkan harapan hidup ODHA secara umum.
Hal itu bisa terjadi karena pengobatan tersebut efektif menekan perkembangan virus dalam tubuh, meningkat imunitas tubuh(khususnya kadar CD4), dan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup.
Jika pelayanan kesehatan untuk masalah HIV/AIDS sudah sedemikian maju dan menunjukkan hasil yang lumayan memuaskan, lantas kenapa tidak semua orang tahu-mau-mampu mengaksesnya?
Terkungkung dalam Stigma
Alasan mendasar masalah tersebut bisa saja beragam dan berbeda-beda tiap orang. Namun secara umum, orang tidak berani berobat karena ingin menyimpan rapat status sakitnya itu agar tidak diketahui orang lain.
Orang enggan terbuka dengan kondisinya pada keluarga atau orang terdekat, lantaran terbebani dengan stigma yang akan diterimanya; apalagi bila dikaitkan dengan “nama baik” keluarga –jangan sampai orang lain tahu!
Sudah banyak studi yang menunjukkan kalau stigma meningkatkan kekhawatiran seseorang untuk membuka statusnya sebagai pengidap HIV. Kalau pun tidak sengaja diketahui orang lain, stigma juga membuat ODHA tidak patuh dengan terapi ARV atau penanganan lainnya.
Saking terbebani, jangankan untuk pergi berobat ke fasilitas kesehatan, rekan dan sanak keluarga lain yang ingin datang menjenguk pun kadang dibatasi.
Kita mungkin pernah atau bahkan sering mendengar ada gosip-gosip yang beredar di lingkungan tempat tinggal. Tentang seseorang yang terlihat sakit parah dengan ciri mengalami perubahan fisik yang sangat drastis dibanding sebelumnya, tetapi ketika ditanya tentang sakit apa yang sedang diderita, jawabannya cenderung tidak jelas.
Upaya menjaga “nama baik” seperti itu justru jadi bumerang. Orang-orang yang penasaran akan membuat asumsi sendiri, sambil terus mencari informasi pada rekan yang lain. Bisa saja dalam proses tersebut, ada rekan yang mengembangkan cerita tidak sesuai fakta.
Gunjingan terus berlanjut dan berkembang semakin liar. Sehingga apa yang tadinya dimaksudkan untuk menutupi aib, malah berubah menjadi sumber desas-desus yang tidak terkendali.
Sebuah kajian yang dilakukan Ade Latifa dan Sri Sunarti Purwaningsih mengemukakan bahwa stigma yang sering dilabelkan pada ODHA sangat berkaitan erat dengan isu seksualitas, gender, etnis, kemiskinan, termasuk juga ketakutan akan terinfeksi virus tersebut.
Sebagai contoh dalam isu seksualitas, kita semua tahu kalau salah satu faktor risiko terjadinya HIV/AIDS adalah hubungan seksual yang tidak aman seperti praktik-praktik seksual atau identitas/orientasi seksual yang berbeda dengan norma yang berlaku pada umumnya; homoseksual; prostitusi; orang yang memiliki perilaku seks bebas, dan penyimpangan seksual lainnya.
Maka ketika ada yang positif HIV, pemberian cap buruk bisa saja mengarah pada ketimpangan tersebut. Padahal, masih banyak faktor risiko lain yang menjadi pemicunya.
Lebih parah lagi, misalnya, kalau stigma-stigma itu muncul sebagai hasil ciptaan dalam pikiran penderita sendiri. Orang lain mungkin biasa-biasa saja, justru penderita yang paranoia; menganggap orang lain akan memberi stigma yang aneh-aneh.
Perlukah Kita Peduli dengan Stigma?
Hidup terkungkung dalam stigma memang sangat tidak mengenakkan. Jika direnung-renung, upaya menyimpan rahasia status penyakit HIV/AIDS karena takut distigma adalah pekerjaan yang sia-sia.
Salah satu upaya penanganan penyakit ini memang berkaitan dengan penekanan stigma, namun sangat tidak mudah dicapai.
Kita sudah merayakan Hari AIDS Sedunia untuk kesekian kalinya. Peringatan khusus ini tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kasus ODHA.
Salah satu poin yang tidak pernah absen untuk dipromosikan adalah ajakan untuk mengurangi stigma pada ODHA dan keluarganya. Peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 berfokus untuk meningkatkan solidaritas masyarakat dunia dalam mempertahankan layanan kesehatan HIV/AIDS yang tangguh.
Peringatan Hari AIDS Sedunia 2020 berfokus untuk meningkatkan solidaritas masyarakat dunia dalam mempertahankan layanan kesehatan HIV/AIDS yang tangguh.
Tema “Global Solidarity, Resilient Services” sangat berkaitan dengan semakin beratnya tantangan penanggulangan HIV/AIDS yang berbarengan dengan pandemi COVID-19.
Salah satu bentuk solidaritas yang dianjurkan, lagi-lagi pesan untuk menghilangkan stigma. Setelah sekian lama diperingati dan diingati, apakah lantas stigma menjadi berkurang?
Tidak! Stigma akan selalu ada dan sulit dikendalikan karena menyangkut pikiran orang lain. Apakah kita mampu mengendalikan pikiran banyak orang di dunia ini?
Tidak mungkin! Karena itu, masa bodoh saja dengan stigma yang dikatakan orang. Tidak usah dimasukkan dalam hati dan pikiran kita.
Kita punya wewenang penuh pada pikiran sendiri. Karena itu, tidak ada gunanya kita menguras energi dan perasaan pada pikiran orang lain yang mustahil untuk dikendalikan. Lebih baik kita fokus pada pikiran sendiri.
Apalagi daya resiliensi ODHA pada stigma dan diskrimasi bersumber dari pikiran dengan mengembangkan rasa optimisme, percaya diri, motivasi diri, empati dan mengendalikan emosi dengan baik.
Sekadar berbagai cerita, bulan September 2020 lalu, saya berkesempatan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Fakultas Keperawatan Unair di Tulungagung, Jawa Timur.
Pada saat itulah, saya pertama kali mendengar wejangan Dosen Pembimbing–Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons)—di hadapan penyintas HIV tentang pentingnya mengendalikan pikiran sendiri dalam menghadapi stigma.
Dosen yang telah banyak berkecimpung dalam riset dan pengembangan Askep HIV/AIDS tersebut menganjurkan kepada para penyintas agar jangan terlalu fokus pada apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain, karena hal itu sangat sulit dikontrol. “Yang utama itu bapak/ibu sendiri. Kalau ingin bahagia, cintailah diri Anda sendiri, sayangi dan terus bersyukur,” tambahnya.
Pada kesempatan itu juga, ada dua (2) ibu rumah tangga yang berbagi pengalaman menjalani hidup sehari-hari sebagai ODHA. Keduanya sama-sama mengakui pentingnya keterbukaan informasi atau status sakit pada orang terdekat. Mulai dengan dengan pasangan hidup (suami) misalnya, kemudian pelan-pelan terbuka pada anggota keluarga besar, lalu berkembang ke masyarakat luas.
Keduanya sama-sama mengaku tidak mudah berterus terang pada awalnya. Takut tidak diterima; takut dikucilkan; dan banyak ketakutan lainnya. Tetapi begitu sudah diketahui keluarga besar, dukungan untuk berobat dan menjalani hidup sebagaimana biasanya dapat berjalan dengan baik. Ketika mereka mengikuti pengobatan ARV secara rutin, kualitas hidup mereka relatif baik dan harapan hidup makin panjang.
Berkaca dari pengalaman tersebut, kita makin yakin kalau sikap terbuka membawa peluang yang lebih baik. Andai kata ketika jujur, pasangan hidup kita tidak mau menerima, masih ada sanak keluarga lain.
Kalau mereka juga tidak terima, masih banyak LSM atau organisasi yang peduli dengan masalah stigma dan diskriminasi seperti ini. Kuncinya jangan diam, carilah informasi dan bantuan pada tempat dan orang yang tepat.
Akan semakin baik bila status HIV diketahui lebih dini, kemudian menjalani terapi ARV juga lebih awal dan patuh. Karenanya sangat penting untuk mengembangkan sikap terbuka. Kalau masih mendengar bisikan-bisikan miring yang sarat stigma, masa bodoh saja!

Oleh: Saverinus Suhardin
Baca juga tulisan lain di kolom Pojok Sehat atau tulisan menarik lainnya dari Saverinus Suhardin