Pada tahun 1985, seorang penulis terkenal Kolombia, Gabriel Garcia Márquez menulis sebuah novel cinta yang fenomenal berjudul “El Amor En Los Tiempos Del Cόlera” (Love in the Time of Cholera).
Tentu saja, nada dasar utama dalam novel ini adalah cinta. Namun, cinta dalam Love in the Time of Cholera bukanlah cinta biasa dan sederhana. Cinta yang direkonstruksi dalam novel ini adalah labirin dengan banyak kejutan di tiap alurnya.
Cinta bukanlah narasi tunggal tanpa dijejali aneka kepahitan, rasa sakit ditinggalkan, penantian yang bertahan, dan harapan akan cinta sejati. Selama setengah abad, Florentino Ariza bertahan dalam cintanya yang menggebu-gebu kepada Fermina Daza yang telah menolak cintanya.
Di tengah wabah Kolera yang mengancam kehidupan manusia pada masa itu, cinta Florentino Ariza tetap bertahan dengan segala kepahitannya.
Tulisan ini tentu tidak akan menyinggung kisah cinta romantis penuh perjuangan antara sepasang kekasih. Love in the Time of Corona adalah refleksi fenomenologis kritis terhadap fakta pandemi Covid-19 yang telah memukul sendi-sendi hidup manusia di seluruh dunia, termasuk masyakat di sekitar kita.
Angka pasien yang terpapar Covid-19 di daerah kita kian meningkat. Angka kematian pun semakin bertambah. Refleksi ini tidak akan berkutat pada jumlah statistika. Yang akan ditelisik dalam tulisan ini adalah rasa sakit psikis (psychical pain) yang diderita oleh masyarakat kita berhadapan dengan ancaman pandemi ini yang langsung membawa seluruh masyarakat manusia pada situasi batas dari kemampuannya untuk bertahan, yakni ancaman kematian yang tak kasat mata.
Kematian menjadi terasa lebih dekat dan mengancam ketika orang-orang yang kita kenal telah menjadi korban. Covid-19 ternyata tidak hanya mengancam kesehatan fisik manusia, melainkan juga kesehatan psikisnya.
Nahasnya, sebagai manusia yang utuh secara jasmani-rohani, keduanya terkait erat. Kecemasan dan ketakutan akan menyerang sistem imun manusia. Demikian pula, rasa sakit yang diderita akan berpengaruh pada kecemasan, ketakutan bahkan mungkin keputusasaan manusia.
Tanggal 14 Februari kita peringati sebagai hari Valentine, yang dihubungkan secara sangat terbatas kepada kasih sayang antar-kekasih. Merayakan Valentine di masa pandemi Covid-19 memaksa kita untuk mendekonstruksi pemahan yang sangat terbatas dan artifisial tentang cinta.
Ketika sebelum pandemi, Valentine dirayakan dengan aneka hadiah yang menimbulkan rasa senang, maka saat ini aneka pemberian dibatasi karena dapat mengancam keselamatan. Cinta tidak bisa lagi diidentikkan dengan sentuhan dan pertemuan. Sebab, ketika pandemi hadir, cinta malah berarti berani menjaga jarak dan menahan keinginan untuk bertemu. Namun, di sinilah cinta menguji kemurniannya.
Ketika ancaman tak kasat mata membayang-bayangi keselamatan hidup kita dan orang-orang kita cintai, maka rasa sakit sebagai fenomen psikis tak bisa kita hindarkan. Lantas, apakah kita sanggup bertahan?
Apakah ada model cinta yang cukup kuat untuk menerima rasa sakit (pain) sebagai bagian yang harus ditanggung demi kelangsungan hidup? Apakah fakta kematian orang-orang yang kita cintai telah membawa kita pada rasa sakit tak tertahankan dalam hidup? Love in the Time of Corona bukan hanya menjadi suatu utopia tanpa dasar. Ia adalah nyala lilin terakhir yang mampu mengisi ruang gelap traumatik dalam diri kita.
Love and Pain
Juan-David Nasio menulis satu elaborasi psikoanalisis yang mendalam tentang hubungan antara cinta dan rasa sakit. Pada tahun 1996, ia menerbitkan sebuah buku berjudul “Le Livre de La Douleur et de L’Amore”, yang versi Inggrisnya diterjemahkan oleh David Pattigrew dan François Raffoul dengan judul “The Book of Love and Pain; Thinking at the Limit with Freud and Lacan”. Dengan bantuan psikoanalisa Freud dan Lacan, Nasio mendalami tema “metapsikologis” tentang hubungan antara cinta (love) dan rasa sakit (pain).
Tesis dasarnya adalah ada keterkaitan tak terputuskan antara cinta dan rasa sakit. Menurutnya, rasa sakit adalah bukti dari kuatnya rasa cinta seseorang. Rasa sakit menghantar manusia pada situasi batas (the limit) yang menjadi pertahanan akhir untuk bertahan dari kegilaan (madness) dan kematian (the death). Rasa sakit ini ada pelbagai tingkatan. Yang paling menyakitkan dari model rasa sakit ini adalah kehilangan orang yang dicintai.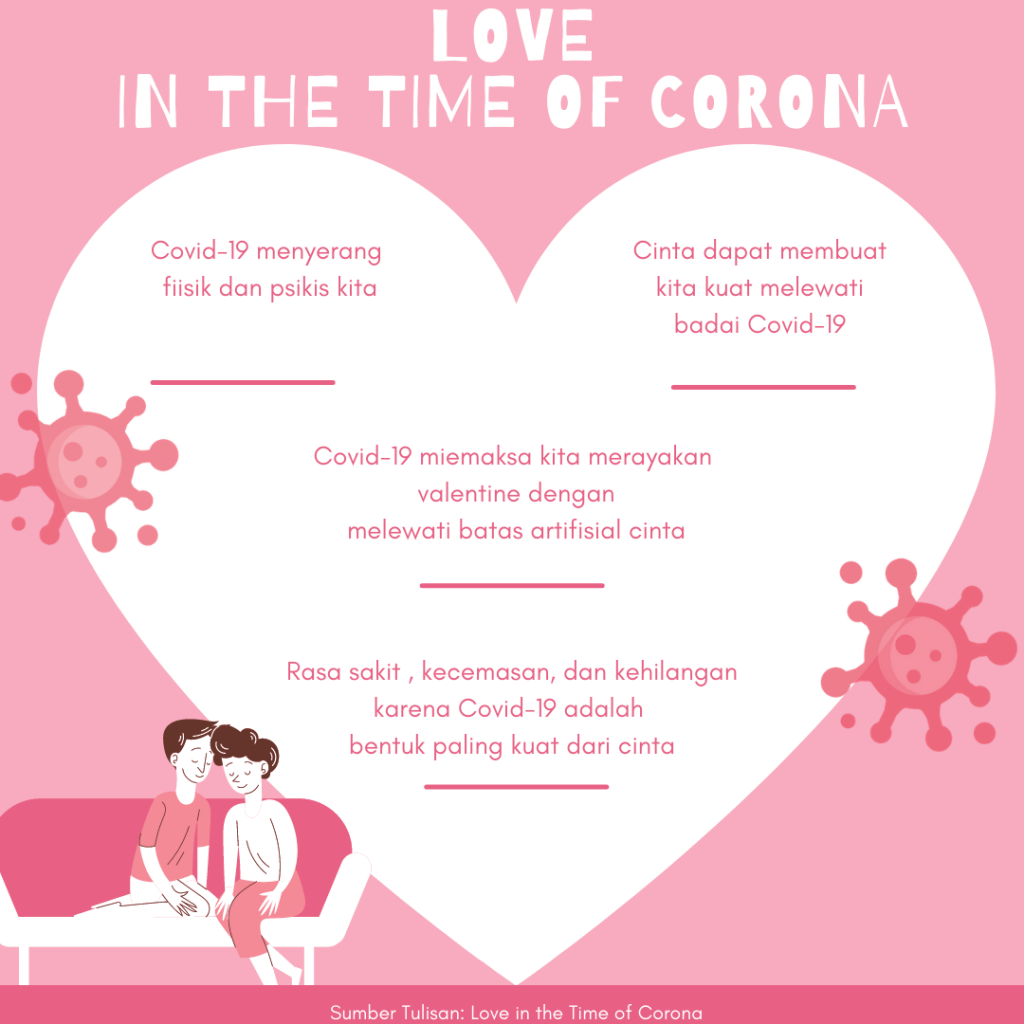 Landasan konseptual Juan David Nasio dimulai dengan penelitian fenomenologis terhadap pengalaman penderitaan pasiennya sendiri yang mengalami penderitaan paska kematian anak yang telah diperjuangkannya.
Landasan konseptual Juan David Nasio dimulai dengan penelitian fenomenologis terhadap pengalaman penderitaan pasiennya sendiri yang mengalami penderitaan paska kematian anak yang telah diperjuangkannya.
Menurut Nasio, penderitaan atau sakit psikis (psychical pain) merupakan pengalaman keterpisahan (separation) dengan objek yang dicintai. Objek yang dicintai ini tidak melulu terbatas pada pribadi manusia, melainkan juga pada objek material lainnya.
Nasio menulis: “Psychical pain is the pain of separation when the separation is uprooting and a loss of an object with which we are so intimately bonded –a person we love, a material thing, a value, or the integrity of our body– that we bond is constitutive ourselves. (Nasio, 2004, hlm. 14)
Nasio punya pemahaman yang optimistik terhadap fenomen penderitaan yang dialami oleh manusia. Baginya, penderitaan erat terkait dengan energi untuk bertahan hidup (survive), alih-alih menyerah diri pada kematian.
Penderitaan yang disadari dan disikapi dengan baik akan membawa kekuatan untuk menyelamatkan diri dari kegilaan dan kematian sebagai bentuk kehancuran eksistensial diri manusia. “Above all, pain is an affect, the ultimate affect, the last defense against madness and death. It is like a final struggle that attests to life and to our power to regain ourselves. One does not die from pain. As long as there is pain, we also have the available forces to fight against it and continue living.” (Nasio, 2004, hlm. 15).
Dengan demikian, rasa sakit atau penderitaan manusia akan menggerakkan dirinya untuk bertahan dan melawan kegilaan dan kematian sebagai upaya untuk melanjutkan kehidupan.
Baca Juga: Semerbak Valentine dan Defisit Cinta Warga Negara Indonesia
Rasa sakit yang dialami manusia memiliki gejala (symptom) sebagai bentujk manifestasi eksterior yang nampak dari pribadi orang yang mengalaminya. Bagi Nasio, sebagaimana Freud, rasa sakit psikis (psychical pain) dan rasa sakit jasmaniah (corporeal pain) dalam konteks psikoanalisa, tidak dapat dipisahkan secara tegas.
Sebab utamanya adalah “pain is a mixed phenomenon, emerging at the limit between the body and the psyche”, rasa sakit merupakan fenomena kompleks yang menyatukan batas difraksi antara tubuh dan jiwa manusia. Dalam istilah kedokteran fenomena ini dapat disebut dengan “psikosomatis”, yakni keterhubungan antara jiwa dan tubuh manusia.
Dalam konteks pandemi, rasa sakit dialami secara dekat dan intim, tidak hanya bagi para penderita Covid-19 sendiri, melainkan dialami pula oleh semua masyarakat, khususnya mereka yang ada dalam lingkaran hidup si penderita. Dengan demikian, bukan hanya soal ancaman sakit jasmaniah (corporeal pain) terhadap sistem imun tubuh, tetapi juga ancaman rasa sakit psikis yang menyerang tanpa melukai secara fisik. Keluarga pasien menjadi cemas.
Kecemasan (anxiety) sudah merupakan bentuk rasa sakit psikis. Ancaman kehilangan orang-orang yang dicintai akan menimbulkan rasa sakit psikis yang akut. Apalagi, keluarga yang de facto mengalami peristiwa kehilangan orang yang dicintai akibat terpapar virus yang mematikan ini.
Baca Juga: Laporan Korban yang Koit dan Kegelisahan Seputar COVID
Kisah pilu teriakan histeris keluarga yang tidak boleh bersentuhan dengan tubuh yang selama ini mereka cintai, bahkan sampai masalah perampasan jenazah dan pengambilan jenazah dari liang kubur adalah fenomena yang menunjukkan betapa rasa sakit kehilangan orang-orang yang dicintai begitu kuat menyerang pertahanan diri seseorang.
Penjarakkan sosial juga menimbulkan rasa cemas dan takut. Orang menjadi asing dengan dirinya sendiri. Keberadaan orang lain dianggap sebagai ancaman yang bisa membahayakan keselamatan diri. Apalagi, dengan adanya istilah kesehatan “Orang Tanpa Gejala” (OTG) yang bisa menjadi vektor pembawa virus yang mematikan ini.
Dalam situasi penuh tekanan seperti ini, kecurigaan menjadi mekanisme mempertahankan diri. Rasa sakit psikis berupa perasaan asing dan terisolasi tidak hanya dialami oleh pasien Covid-19 di ruang isolasi, melainkan juga dirasakan oleh banyak masyarakat yang terkurung dalam perasaan takut dan terancam.
Di saat rentan seperti ini, kejahatan kemanusiaan yang terjadi dari oknum pejabat pemerintahan, seperti korupsi dana bantuan Covid turut membentuk sikap antipati masyarakat. Belum lagi, aneka disinformasi dengan pelbagai tafsiran tentang teori konspirasi serta kecurigaan terhadap institusi kesehatan memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap ketakutan masyarakat. Aneka masalah sosial ini dapat dikerucutkan dalam satu fenomena psikososial, yakni: “ketidakpercayaan” (distrust).
Dari refleksi Nasio, kita mendapatkan suatu pencerahan secara internal bahwa rasa sakit yang kita alami di saat pandemi ini adalah bukti bahwa tubuh dan jiwa kita sedang berjuang untuk mempertahankan ikatan kita dengan seseorang atau sesuatu yang kita cintai.
Bertahan dalam rasa sakit adalah cara kita mempertahankan ikatan cinta kita. Sebab kegilaan (madness) sebagai bentuk paling buruk dari keputusasaan adalah cara untuk lari dari kenyataan rasa sakit ini.
Omnia Vincit Amor
Setelah mendalami fenomena rasa sakit, baik secara fisik maupun psikis, kita akan mencari suatu peganganan yang dapat membuat kita bertahan melewati aneka rasa sakit yang timbul dari ancaman pandemi Covid-19 ini. Jika rasa sakit adalah mekanisme eksistensial dari keseluruhan diri manusia untuk bertahan dalam situasi batas, maka kekuatan untuk bertahan dalam rasa sakit eksistensial tersebut adalah cinta itu sendiri.
Jika pandemi Covid-19 menggiring seluruh masyarakat manusia dalam situasi batas yang penuh kerapuhan, maka cinta menjadi kekuatan untuk bertahan menanggung rasa sakit dan menolak jatuh dalam kekosongan dan kegilaan.
Love in the Time of Corona adalah pelita harapan di tengah kepungan kegelapan pandemi yang mengancam eksistensi hidup manusia. Secara medis, vaksin mungkin menjadi harapan terakhir kita untuk melawan ganasnya ancaman virus Covid-19. Namun, cinta yang sejati adalah energi besar yang menjadikan kita kuat bertahan untuk melewati semua pengalaman pahit dan rasa sakit yang tidak sedikit ini.
Cintalah yang membuat kita bertahan untuk tetap merawat kesehatan dan mematuhi protokol. Kepatuhan karena ancaman berbeda dengan kepatuhan karena cinta. Kepatuhan karena ancaman (misalnya berupa sanksi) itu memperbudak, sedangkan kepatuhan karena cinta itu memerdekakan. Kita taat Prokes bukan karena takut terhadap Pemerintah atau menghindari sanksi. Kita taat karena kita mencitai hidup yang dianugerahkan secara cuma-cuma kepada kita. Kita taat karena kita mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita.
Kita bertahan dalam situasi hidup yang serba sulit. Siswa-siswa kehilangan kesempatan untuk belajar bersama sahabat dan mengalami situasi kelas. Para umat beragama merindukan ibadah bersama di tempat ibadahnya masing-masing.
Semua masyarakat ingin merasakan indahnya berkumpul bersama dalam aneka kegiatan dan juga ritual adat. Namun, semua kerinduan ini sedang diuji oleh pandemi Covid-19. Cintalah yang mampu menyalakan harapan bagi kita dan menguatkan kita bahwa setelah pekat gelap pandemi ini, pasti terbit terang harapan. Love wins everything. Omnia vincit amor.
*) Gagasan kolumnis ini adalah sepenuhnya tanggungjawab penulis seperti tertera dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi

Oleh: Giovanni A. L Arum
Baca juga tulisan lain di kolom Gagasan atau tulisan menarik lainnya dari Giovanni A. L Arum




